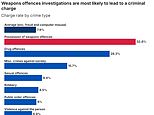DElia Hawass berusia 24 tahun ketika serangan udara Israel menghancurkan gedung apartemen tempat dia tinggal pada bulan Februari, menguburkan ibu mudanya dan putrinya yang berusia 10 bulan, Mona. Jenazah mereka tidak termasuk di antara korban tewas perang di Gaza karena mereka terjebak terlalu dalam di bawah reruntuhan sehingga tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka.
Sepuluh bulan setelah perang Israel di Gaza, jumlah korban tewas telah melebihi 40.000, menurut otoritas kesehatan di Jalur Gaza. Sebagian besar korban tewas adalah warga sipil, dengan total korban jiwa mencapai hampir 2% dari populasi Gaza sebelum perang, atau satu dari 50 penduduk.
Namun angka ini pun tidak menceritakan keseluruhan kerugian yang dialami Palestina. “Angka 40.000 ini hanya mencakup jenazah yang diterima dan dikuburkan,” kata Dr. Marwan al-Hams, kepala rumah sakit lapangan Kementerian Kesehatan Palestina. “Prosedur baru untuk memasukkan orang hilang dan orang-orang yang diketahui berada di bawah reruntuhan ke dalam daftar kematian sedang diuji tetapi belum disetujui.”
Sekitar 10.000 korban serangan udara diyakini masih terkubur di dalam bangunan yang runtuh, kata Hams, karena hanya ada sedikit alat berat atau bahan bakar untuk menggali dan mencari reruntuhan baja dan beton.
“Setiap kali saya memikirkan Dalia, saya mulai menangis dan gemetar,” kata ibunya, Fatima Hawass. “Saya merasa tercekik ketika memikirkan rumahnya yang dibongkar, karena bahkan setelah jiwanya pergi, kami belum dapat mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara layak. Itu sebabnya.”
Dalia, lulusan bahasa dan sastra Arab, gemar membaca dan bercita-cita menjadi guru, ujarnya. “Kadang-kadang aku masih melihatnya dalam mimpiku. Aku terbangun sambil menangis, tapi ini membuatnya sedikit lebih mudah.”
Kelompok korban perang Palestina lainnya tidak muncul dalam statistik resmi, yang hanya mencatat mereka yang tewas akibat bom dan peluru sebagai korban perang.
Selama 10 bulan terakhir, perang telah menyebabkan sejumlah besar pengungsi mengungsi ke tempat penampungan yang penuh sesak dan tenda-tenda darurat, menyebabkan kelaparan karena berkurangnya pasokan bantuan, dan kurangnya air bersih dan sanitasi yang kronis sehingga menyebarkan penyakit.
Rumah sakit telah dibom dan dikepung, persediaan obat-obatan, peralatan dan bahan bakar terputus, staf medis ditahan atau dibunuh, dan bangsal dibanjiri air.
“Ini tidak termasuk orang-orang yang meninggal akibat dampak tidak langsung perang, seperti penyakit, kelaparan, atau runtuhnya sistem medis,” kata Hammes. “Sebuah komisi akan dibentuk untuk menghitung (para korban) ini dan pekerjaan akan dimulai segera setelah perang berakhir.”
Di antara ribuan orang yang mungkin masuk dalam daftar tersebut adalah nenek Rania Abu Samra yang berusia 75 tahun, Hania Abu Samra, dan ayahnya yang berusia 59 tahun, Adnan Abu Samra.
Menurut Rania, Hania pingsan dan meninggal di depan cucunya pada November lalu setelah keluarganya berjalan seharian dari Gaza utara ke Gaza selatan. Mereka meninggalkan rumah mereka dengan berjalan kaki setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi di daerah tersebut, karena mereka tidak memiliki alat transportasi lain.
Rania mengatakan Adnan meninggal karena infeksi dada kurang dari tiga bulan kemudian, setelah berulang kali ditolak oleh rumah sakit yang ramai.
Menurutnya, ayahnya adalah seorang pria energik yang menderita diabetes dan tekanan darah tinggi bahkan sebelum perang, namun dia menghabiskan musim dingin di tempat penampungan plastik darurat tanpa pemanas, memasak di atas api yang terbuat dari kayu bekas dan plastik bahwa paru-parunya telah rusak akibat tindakan tersebut. Saat dokter memeriksanya, semuanya sudah terlambat.
“Jika tidak ada perang, dia tidak akan meninggalkan kita secepat ini. Dia tidak akan berusia 60 tahun,” katanya. “Kepergiannya sangat mempengaruhi kami. Dia adalah penghubung utama dalam keluarga kami dan melakukan apa pun yang kami butuhkan.”
“Saya yakin ada ribuan orang lain seperti ayah saya, tapi tidak ada yang tahu tentang mereka dan mereka tidak ada dalam daftar korban tewas,” kata Rania. “Jangan anggap mereka hanya sekedar angka. Mereka punya kehidupan yang harus dijalani, mereka punya keluarga dan teman, dan mereka pergi tanpa pamit.”
Pihak berwenang Israel mempertanyakan jumlah korban tewas yang diumumkan oleh otoritas Gaza. Mereka mengatakan otoritas kesehatan tidak dapat memberikan angka yang dapat diandalkan karena Hamas mengendalikan pemerintahan Gaza, namun para dokter dan pegawai negeri yang menjalankan rumah sakit dan sistem kesehatan memiliki catatan yang dapat diandalkan mengenai perang di masa lalu di Gaza.
Setelah berbagai konflik antara tahun 2009 dan 2021, penyelidik PBB menyusun daftar korban tewas mereka sendiri dan menemukan bahwa daftar tersebut sangat cocok dengan daftar korban tewas di Jalur Gaza.
“Sayangnya, kami mempunyai pengalaman menyedihkan dalam merekonsiliasi jumlah korban dengan Kementerian Kesehatan setiap beberapa tahun,” kata Farhan Haq, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB. dikatakan. “Jumlah mereka telah terbukti akurat.”
Jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza tidak dipecah menjadi kombatan dan warga sipil, namun pada akhir Juni, 28.185 jenazah korban pertempuran telah diidentifikasi.
Mayoritas dari mereka dianggap warga sipil karena usia dan jenis kelamin, termasuk 9.351 anak-anak, 5.320 perempuan, dan 2.414 lansia. Jumlah ini lebih dari 17.000 warga sipil, belum termasuk banyak pria sipil usia tempur yang tewas dalam aksi tersebut.
Israel tidak memperkirakan jumlah korban sipil di Gaza, namun militer mengatakan mereka telah menewaskan sekitar 15.000 pejuang. Israel memulai perang setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. 250 orang lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera.
Laju kematian di Gaza sedikit melambat tahun ini dibandingkan tahun 2023. Para pejabat kesehatan mengatakan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 22.000 orang pada tanggal 31 Desember, lebih banyak dari jumlah kematian sejauh ini pada tahun 2024.
Namun, jumlah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara Israel dan Palestina dan secara historis sangat tinggi. Bom-bom besar dijatuhkan setiap hari, seringkali menewaskan puluhan orang. Pada hari Sabtu, sekolah yang dulunya digunakan sebagai pusat evakuasi terkena serangan udara.
Mereka yang tertinggal dalam setiap serangan tidak hanya harus menghadapi kesedihan tetapi juga trauma hidup dalam bayang-bayang kematian dan ancaman serangan baru yang terus-menerus.
Pada bulan November, serangan udara menghancurkan apartemen Ali Abbas, menewaskan dua anaknya, Fatima, 17, dan Omar, 5, serta saudara laki-lakinya dan dua keponakannya, salah satunya berusia 20 hari. Tidak ada rekomendasi atau peringatan evakuasi yang dikeluarkan.
Abbas terluka parah dan menghabiskan dua minggu dalam perawatan intensif, awalnya terlindung dari berita kematian anak-anaknya. Ketika dia diberitahu hal ini, dia mencoba melepaskan semua tabung yang membuatnya tetap hidup. Anggota keluarga yang tersisa saat ini tinggal di tenda.
“Kami selalu bilang kami akan tinggal di rumah ibu saya, tapi anak saya menderita fobia terhadap bangunan dan tembok, dan bangunan itu menimpa kami saat pemboman terjadi, dan orang-orang keluar dari bawah reruntuhan untuk menjemputnya. Saya menolak karena saya takut kegelapan karena saya harus memaksakan diri keluar.”
“Saya terbangun karena teriakannya. Dia selalu mengalami mimpi buruk saat dia masih berada di bawah reruntuhan dan memohon, ‘Tolong, tolong, tolong.’