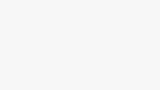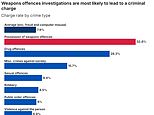Gambar Getty
Gambar GettyPenulis dan penyair yang terkenal secara internasional, Mia Kouto, menggambarkan dirinya sebagai orang Afrika, namun akarnya ada di Eropa.
Orang tuanya yang berkebangsaan Portugis menetap di Mozambik pada tahun 1953 setelah melarikan diri dari kediktatoran Antonio Salazar.
Kuto lahir dua tahun kemudian di kota pelabuhan Baira.
“Masa kecil saya sangat bahagia,” katanya kepada BBC.
Ia mengklaim bahwa ia sadar akan kenyataan bahwa ia hidup dalam “masyarakat kolonial” – tidak ada yang perlu menjelaskan hal ini kepadanya, karena “batas antara kulit putih dan kulit hitam, antara miskin dan kaya sangat jelas”.
Sebagai seorang anak, Kuto pemalu dan cacat, tidak mampu berbicara sendiri di depan umum atau bahkan di rumah.
Sebaliknya, seperti ayahnya, seorang penyair dan jurnalis, ia menemukan hiburan dalam kata-kata tertulis.
“Saya menemukan sesuatu, menjalin hubungan dengan koran, dan di balik koran itu selalu ada seseorang yang saya cintai, mendengarkan saya: ‘Ini dia’,” katanya kepada BBC dari rumahnya di Maputo, ibu kota Mozambik. Lukisan warna-warni dan ukiran kayu di dinding berwarna kuning mustard sebagai latar belakang.
Karena berasal dari Eropa, Couto – “asimilados” – elit kulit hitam di kolonial Portugis Mozambik – dianggap, dalam bahasa rasis saat itu, cukup “beradab” untuk menjadi warga negara Portugis.
Penulis menganggap dirinya beruntung bisa bermain dengan anak-anak Assimilados dan mempelajari sebagian bahasa mereka.
Dia mengatakan hal itu membantunya menyesuaikan diri dengan mayoritas kulit hitam.
“Satu-satunya saat saya ingat menjadi orang kulit putih adalah ketika saya berada di luar Mozambik. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi di Mozambik,” katanya.
Namun, sebagai seorang anak, dia tahu bahwa warna putih membedakannya.
“Tidak ada seorang pun yang mengajari saya tentang ketidakadilan masyarakat di tempat saya tinggal. Dan saya berpikir: ‘Saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri. “Saya tidak bisa bahagia tanpa berjuang melawannya,” katanya.
 Gambar Getty
Gambar GettyKetika Couto berusia 10 tahun, perjuangan melawan kekuasaan Portugis di Mozambik dimulai.
Sebagai seorang pelajar berusia 17 tahun yang menulis puisi untuk sebuah terbitan anti-kolonial dan sangat ingin bergabung dalam perjuangan pembebasan, penulisnya mengenang malam ia dipanggil untuk menghadap Frelimo, para pemimpin gerakan revolusioner.
Saat mencapai tempat tinggal mereka, dia mendapati dirinya satu-satunya anak laki-laki kulit putih di kelompok yang terdiri dari 30 orang.
Para pemimpin meminta semua orang yang hadir untuk menggambarkan apa yang mereka alami dan mengapa mereka ingin bergabung dengan Freelimo.
Kuto adalah orang terakhir yang berbicara. Saat dia mendengarkan cerita tentang kemiskinan dan kekurangan, dia menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di ruangan itu.
Jadi, dia mengarang cerita tentang dirinya sendiri – kalau tidak, dia tahu tidak mungkin dia terpilih.
“Tetapi ketika tiba giliran saya, saya tidak bisa berkata-kata dan diliputi emosi,” ujarnya.
Yang menyelamatkannya adalah para pemimpin Frelimo telah menemukan puisinya dan memutuskan bahwa dia dapat membantu perjuangan mereka.
“Pria yang memimpin pertemuan itu bertanya kepada saya: ‘Apakah Anda pemuda yang menulis puisi di surat kabar?’ Dan saya berkata: ‘Ya, saya seorang penulis.’ Dan dia berkata: ‘Baiklah, Anda bisa datang, Anda bisa menjadi bagian dari kami karena kami membutuhkan puisi,'” kenang Couto.
Setelah Mozambik memperoleh kemerdekaan dari Portugal pada tahun 1975, Couto terus bekerja sebagai jurnalis di media lokal hingga meninggalnya presiden pertama Mozambik, Samora Machel, pada tahun 1986.
“Ada semacam keretakan; Saya tidak lagi percaya pada wacana libertarian,” katanya.
Setelah melepaskan keanggotaan Frelimo, Couto belajar biologi. Saat ini, ia bekerja sebagai ahli ekologi dengan spesialisasi di wilayah pesisir.
Ia pun kembali menulis.
“Awalnya saya mulai dengan puisi, lalu buku, cerita pendek, dan novel,” katanya.
Novel pertamanya, Sleepwalking Land, diterbitkan pada tahun 1992.
Ini adalah fantasi realis magis yang terinspirasi oleh perang saudara pasca-kemerdekaan di Mozambik, membawa pembaca melalui konflik brutal dari tahun 1977 hingga 1992 antara Renamo – sebuah gerakan pemberontak yang didukung oleh rezim minoritas kulit putih yang saat itu berada di Afrika Selatan dan Barat. Kekuatan – melawan Frelimo.
Buku itu langsung sukses. Buku tersebut digambarkan oleh para juri di Pameran Buku Internasional Zimbabwe pada tahun 2001 sebagai salah satu dari 12 buku Afrika terbaik abad ke-20 dan telah diterjemahkan ke lebih dari 33 bahasa.
Couto dikenal karena lebih banyak novel dan cerita pendeknya yang membahas tentang perang dan kolonialisme, rasa sakit dan penderitaan yang dialami masyarakat Mozambik, dan ketahanan mereka di masa-masa sulit tersebut.
Tema lain yang dia fokuskan termasuk ilmu sihir, agama, dan interpretasi spiritual yang berasal dari cerita rakyat.
“Saya ingin memiliki bahasa yang dapat menerjemahkan berbagai aspek di Afrika, hubungan dan dialog antara yang hidup dan yang mati, yang terlihat dan yang tidak terlihat,” katanya kepada BBC.
Couto populer di seluruh dunia berbahasa Portugis – Angola, Tanjung Verde dan Sao Tome di Afrika, serta Brasil dan Portugal.
Pada tahun 2013, dia memenangi Hadiah Camos €100,000 ($109,000; £85,500), anugerah terbesar untuk penulis dalam bahasa Portugis.
Pada tahun 2014 ia dianugerahi Neustadt senilai $50.000 (£39.000), yang dianggap sebagai hadiah sastra paling bergengsi setelah Nobel.
Ketika ditanya apakah karyanya mencerminkan realitas Afrika modern, Couto menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin karena benua tersebut terbagi dan terdapat begitu banyak Afrika yang berbeda.
“Kami tidak mengenal satu sama lain dan kami tidak mempublikasikan penulis kami sendiri di benua kami karena batasan bahasa kolonial seperti Prancis, Inggris, dan Portugis,” katanya.
“Kami mewarisi struktur kolonial, yang sekarang “dinaturalisasi”, menjadi Afrika Anglophone, berbahasa Perancis dan Lusophone,” katanya.
Kuto dijadwalkan menghadiri festival sastra di Kenya bulan lalu, namun sayangnya harus membatalkan perjalanan tersebut setelah terjadi protes besar-besaran terhadap Presiden William Ruto. Bergerak untuk menaikkan pajak.
Ia berharap akan ada peluang lain untuk mempererat hubungan dengan para penulis dari wilayah lain di Afrika.
“Kita harus mendobrak hambatan-hambatan ini. Kita harus lebih mementingkan pertemuan yang kita lakukan sebagai warga Afrika dan antar warga Afrika,” kata Couto.
Dia menyesalkan bahwa para penulis Afrika terus-menerus memandang Eropa dan Amerika Serikat sebagai titik referensi dan enggan merayakan keberagaman dan hubungan mereka dengan dewa dan nenek moyang mereka.
“Faktanya, kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi secara artistik dan budaya di luar Mozambik. Tetangga kami – Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, Tanzania – kami tidak tahu apa-apa tentang mereka dan mereka tidak tahu apa-apa tentang Mozambik,” kata Couto.
Ketika ditanya nasihat apa yang akan dia berikan kepada penulis muda yang baru memulai, dia menekankan perlunya mendengarkan suara orang lain.
“Mendengarkan bukan sekedar mendengar suara atau melihat iPhone atau gadget atau tablet. Ini lebih tentang mampu menjadi sesuatu yang lain. Ini semacam migrasi, migrasi tak kasat mata untuk menjadi orang lain,” kata Couto.
“Jika seorang tokoh dalam buku menyentuhmu, itu karena tokoh itu sudah ada di dalam dirimu dan kamu tidak mengetahuinya.”
Anda mungkin juga tertarik pada:
 Gambar Getty/BBC
Gambar Getty/BBC