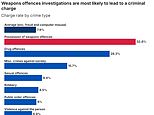WKetika Carol Edwards dan putrinya pergi berjalan-jalan di akhir pekan ke Holnicote House, sebuah hotel di Exmoor di Somerset, seorang pemandu mengajak mereka berkeliling properti tersebut, menjelaskan sejarah 500 tahun properti tersebut. “Kisahnya berakhir sekitar tahun 1945,” kata Edwards. “Jadi setelah itu, saya berkata kepadanya: ‘Kamu melewatkan satu bagian.’” Edwards mengetahui hal ini karena dia telah tinggal di Holnicote House selama lima tahun pertama dalam hidupnya, bersama dengan 25 anak lain seperti dia, segera setelah Perang Dunia Kedua. perang. Semua anak-anak tersebut yatim piatu, semuanya ras campuran: ibu mereka adalah wanita kulit putih Inggris, ayah mereka adalah GI Afrika-Amerika yang ditempatkan di Inggris selama perang.
Edwards adalah salah satu dari apa yang disebut oleh surat kabar AS sebagai “bayi coklat”. Setidaknya 2.000 dari anak-anak ini lahir selama perang, pada saat hanya terdapat 7-10.000 orang kulit hitam di seluruh Inggris. Jadi “bayi coklat” ini meningkatkan populasi warga kulit hitam Inggris sekitar 25 persen. Lebih dari setengahnya diyakini telah diserahkan untuk diadopsi, tetapi Holnicote House, yang diambil alih oleh dewan daerah Somerset pada tahun 1943, adalah satu-satunya rumah anak yang didedikasikan khusus untuk mereka. Edwards, 79, memiliki kenangan positif selama berada di sana. “Mereka peduli pada kami dan mereka mencintai kami semua,” katanya. “Kami semua diperlakukan sama dan tidak pernah dibuat merasa berbeda… Saya merasa sangat terhormat bisa menghabiskan lima tahun pertama saya di sana. Saya pikir saya adalah salah satu yang beruntung.”
Untuk “bayi coklat” lainnya gambarannya lebih bervariasi, kata Chamion Caballero, salah satu pendiri Museum Campuranarsip digital sejarah percampuran ras di Inggris. Mereka mempunyai stigma ganda, yaitu ras campuran dan dilahirkan di luar nikah, dan mereka diperlakukan sebagai masalah oleh pihak berwenang. “Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka,” katanya. Kebanyakan dari mereka mendapati diri mereka satu-satunya orang kulit berwarna di daerah pedesaan yang sangat berkulit putih, tempat mereka menonjol, mengalami diskriminasi, dan tidak memiliki hubungan dengan komunitas kulit hitam. Mereka yang tertarik pada komunitas kulit hitam di kota-kota seperti London, Liverpool atau Bristol juga sering menghadapi diskriminasi karena “tidak cukup hitam”.
Setelah AS bergabung dalam perang pada tahun 1942, dua hingga tiga juta GI melewati Inggris, dan diperkirakan 840.000 di antaranya berkulit hitam. Ini adalah benturan budaya di beberapa bidang. Ini masih sebelum hak-hak sipil, era Jim Crow dan militer AS dipisahkan. Tentara kulit hitam sebagian besar diberi peran non-tempur seperti pendukung darat, katering, pembersihan, mengemudi, dan konstruksi – sebagian besar adalah pekerja kulit hitam yang membangun 200 pangkalan AS di sekitar Inggris, yang sebagian besar berada di daerah pedesaan: East Anglia, wilayah selatan- barat, pantai selatan dan Wales selatan.
Bukan hanya pengaturan tempat tinggal dan pekerjaan pasukan Amerika yang dipisahkan; begitu pula waktu luang mereka, jelas Lucy Bland, profesor sejarah sosial dan budaya di universitas Anglia Ruskin dan penulis “Bayi Coklat” di Inggris: “Kota atau desa akan ditetapkan sebagai ‘Hitam’ pada hari-hari tertentu dan ‘putih’ pada hari-hari lainnya.” Oleh karena itu, segregasi Amerika diberlakukan di wilayah-wilayah Inggris – yang juga melibatkan banyak orang yang menganggap diri mereka bersekutu dalam perjuangan melawan fasisme.
Menurut Caballero, banyak masyarakat setempat yang lebih memilih ditemani GI Hitam dibandingkan GI kulit putih. “Orang kulit putih Inggris sering menganggap orang kulit putih Amerika cukup arogan,” katanya. “Padahal mereka menemukan bahwa tentara Kulit Hitam sangat ramah; mereka sangat sopan, mereka sangat hangat, mereka tidak memandang rendah orang. Namun sikap tersebut mulai sedikit berubah ketika anak-anak mulai lahir. Jadi semuanya seperti ini: ‘Senang rasanya menjadi teman, senang menjadi sekutu. Belum tentu menginginkanmu sebagai menantu.’”
Ann Evans, yang juga tinggal di Holnicote, mengatakan ibunya bekerja di sebuah bar di Castle Cary: “Di sanalah dia bertemu ayah saya.” Ayah Evans berasal dari Mississippi. Dia belum menikah, dan berencana kembali belajar akuntansi setelah perang. Dia menjadi pengunjung tetap di pub ibunya pada malam-malam “Hitam” itu. “Mereka mengadakan pesta pada malam terakhir sebelum hari H, dan begitulah cara mereka berkumpul.”
Ayah Edwards adalah seorang sersan dari Detroit, yang ditempatkan di Somerset. Ibunya sudah menikah dan sudah memiliki lima anak; suaminya sedang pergi berperang di Italia (dan tampaknya tidak pernah mengetahui tentang Edwards). Kedua wanita tersebut diserahkan untuk diadopsi beberapa hari setelah kelahiran mereka dan dikirim ke Holnicote. Seringkali hanya ada sedikit alternatif. Para ayah, meskipun mereka tahu bahwa mereka adalah ayah, akan kembali ke AS di mana pernikahan antar ras masih ilegal di 30 negara bagian. Bahkan jika mereka ingin tetap tinggal, mereka hanya bisa menikah dengan izin dari komandan mereka (yang biasanya berkulit putih), yang biasanya ditolak. Seorang ibu asal Inggris yang menikah dengan pasangannya yang berkulit hitam di negara bagian selatan dideportasi dan suaminya dipenjara, kata Bland.
Para perempuan ini, yang berasal dari komunitas pedesaan yang erat, menghadapi tekanan yang sangat besar untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk diadopsi. Dalam keluarga yang memelihara anak ras campuran, sering kali neneklah yang membesarkan anak mereka, untuk menghindari stigmatisasi terhadap ibu atau membahayakan peluang mereka untuk menikah. “Wanita yang mengasuh anak mereka mengalami masa-masa sulit,” kata Bland. “Mereka diludahi di jalan. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan.” Tentu saja, ada banyak anak GI kulit putih yang lahir dengan cara yang sama, tapi mereka lebih mudah disembunyikan.
Holnicote mendorong keluarga setempat untuk mengadopsi anak-anak ini, dan itulah yang terjadi pada Evans. “Ibuku sangat menginginkan anak perempuan, karena dia mempunyai semua anak laki-laki,” katanya. Semalam, Evans pindah ke Abertillery, di Wales selatan (dia berbicara dengan aksen Welsh yang lembut), di mana dia memperoleh seluruh jaringan keluarga: orang tua, kakek-nenek, dan empat saudara laki-laki. Ayah ibunya telah memperingatkan agar tidak mengadopsi anak ras campuran, namun ibunya tidak peduli, kata Evans. “Saya rasa dia tidak menyadari reaksi orang lain saat itu, di awal tahun 50an, karena ketika mereka melihat saya, dan ibu mengatakan saya adalah putrinya, mereka tentu berasumsi dia pergi bersama pria kulit hitam. Dia bukan wanita yang akan selingkuh dari suaminya.”
Evans mengingat perasaan “berbeda” yang samar-samar. “Segera setelah saya sampai di lembah, saya diberitahu secara blak-blakan, dan saya disuruh kembali ke tempat asal saya. Dan ini dari orang dewasa, bukan anak-anak.” Dia berasumsi yang dimaksud adalah Somerset. “Saya memiliki aksen Somerset pada saat itu, dan seringkali saya tidak dapat memahami apa yang orang katakan kepada saya karena aksen Welsh sangat kental di lembah. Saya biasa memandangnya dengan agak bodoh.” Namun, orang tuanya dan saudara laki-lakinya selalu membelanya, katanya.
Edwards dipindahkan ke panti asuhan dekat Taunton bersama anak laki-laki lain dari Holnicote, tempat mereka tinggal dari usia lima hingga 12 tahun. “Kami adalah satu-satunya anak ras campuran di sana, namun kami tidak dibuat merasa berbeda dari anak-anak lainnya,” dia mengatakan. Ayahnya telah menulis surat ke rumah tersebut dan mencoba membawanya ke AS untuk tinggal bersama keluarga barunya, namun pihak berwenang memutuskan bahwa dia akan lebih baik jika berada di tempat dia berada, katanya. “Dia berusaha sangat keras, tapi pada akhirnya, dia menyerah begitu saja.”
Dia pindah ke rumah lain di Buckinghamshire, dan diadopsi pada usia 14 tahun oleh pasangan “baik dan luar biasa” yang tinggal di dekat High Wycombe dan memiliki seorang putra dewasa dengan anak sendiri. Seperti Evans, dia merasa terhubung dengan jaringan keluarga yang penuh kasih; tapi sekali lagi, dia satu-satunya orang kulit hitam di sekolahnya. Ketika anak-anak bertanya dari mana asalnya, dia tidak bisa menjawabnya.
Tak satu pun dari anak-anak Holnicote yang tahu banyak tentang latar belakang mereka. “Kami sama sekali tidak tahu mengapa kami berada di sana atau apa yang menanti kami di masa depan,” kata Edwards. Hal ini biasa terjadi, kata Bland. “Ada satu, Sandy, yang berada di panti asuhan di Bristol, dan dia melihat ke cermin – dia berusia 14 tahun – dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berkulit hitam. Dan dia berkata kepada teman-temannya: ‘Mengapa kamu tidak memberitahuku?’”
“Saya menemukan siapa saya sebenarnya melalui musik,” kata Edwards. “Saya tahu kedengarannya konyol, tapi saya menyukai penyanyi seperti Sarah Vaughan, Billy Eckstine, Nina Simone, Shirley Bassey. Dan baru setelah saya mengetahui bahwa mereka berkulit hitam, saya menyadari: ‘Saya seperti mereka.’” Orang tua Edwards tidak memberi tahu dia bahwa dia diadopsi sampai hari pernikahannya, pada usia 18 tahun, ketika mereka menyerahkan surat adopsi kepadanya. dan berkata: “’Sekarang kamu sudah menikah, ini adalah milikmu.’ Ibuku berkata: ‘Hari dimana aku memberimu ini akan menjadi hari dimana kamu tidak ingin memanggilku ibu lagi.’ Dan saya berkata: ‘Itu tidak akan pernah terjadi.’ Jadi dia mengambil kembali surat-surat itu, dan saya tidak pernah melihatnya sejak hari itu sampai sekarang.”
Evans menunggu hingga usia akhir 30-an, ketika orang tuanya meninggal, untuk mulai mencari ibu kandungnya. Layanan sosial mengatakan kepadanya: “Kami telah menemukan ibumu, tapi dia tidak ingin berurusan denganmu.” Ketika dia meninggal, Evans mendekati putri ibunya, saudara tiri Evans, yang tidak mengetahui apa pun tentang keberadaannya. Mereka berbicara dan dia menyadari bahwa ibu kandungnya “tampaknya bukan wanita yang baik. Dan dia tidak terlalu baik pada (setengah) saudara perempuanku. Akhirnya saya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dia.” Dia mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal pada usia 49 tahun. Dia telah menikah dan mereka memiliki seorang putra angkat. Jandanya menolak bertemu Evans. “Dia berkata: ‘Apa yang membuatmu berpikir aku ingin bertemu dengan kecerobohan suamiku?’ Dan saya berkata: ‘Keingintahuan?’” Setidaknya dia mengirimi Evans fotonya.
Edwards tidak pernah menemukan ibu kandungnya dan terus mencari informasi tentangnya (dia tinggal di South Cadbury, Somerset, dan nama belakangnya adalah Conners). Dia melakukan perjalanan ke Florida untuk bertemu ayahnya ketika dia berusia pertengahan 30-an. “Rasanya cukup canggung bagi saya,” kenangnya, “karena kami dikelilingi oleh anggota keluarga, dan saya lebih suka menghabiskan waktu sendirian bersamanya.”
Kedua wanita tersebut menikah dan memiliki anak serta cucu, dan keduanya kini berhubungan dengan keluarga Amerika mereka, dan dengan mantan penduduk Holnicote lainnya. “Apa yang semakin sering kita lihat adalah anak-anak dan cucu-cucu merekalah yang mengeksplorasi sejarah keluarga,” kata Caballero, “dan sering kali mendukung orang tua atau kakek-nenek mereka serta menyemangati mereka, karena kerahasiaan dan rasa malu yang terkandung dalam sejarah tersebut. ”
Tes DNA telah menjadi aset besar dalam pencarian ini, kata Caballero. Seperti yang telah terjadi Jejak GIsebuah kelompok sukarelawan yang berdedikasi untuk membantu keturunan GI Amerika (dari semua ras) untuk menemukan kerabat mereka. Museum Campuran adalah sumber lainnya. Benang-benang sejarah yang hilang kini diikat kembali. Edwards dan Evans baru-baru ini kembali ke Holnicote House untuk merekam podcast untuk National Trust (yang memiliki dan mengelola Perkebunan Holnicote), bersama dengan Bland dan sejarawan David Olusoga. “Saya selalu merasa sedikit emosional,” kata Edwards, “karena kenangannya begitu kuat, dan itu adalah saat-saat yang sangat indah.” Evans setuju: “Rasanya seperti pulang ke rumah. Karena walaupun saya sudah tinggal di Abertillery selama bertahun-tahun, saya tidak pernah merasa seolah-olah itu adalah rumah saya. Saya selalu merasa seperti orang yang aneh.”