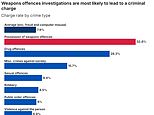Perang Israel di Gaza diwujudkan dalam berbagai bentuk brutal, yang paling berbahaya dan menghancurkan adalah penggunaan senjata kelaparan. Pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa “tidak akan ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar” yang diizinkan di Gaza. Pembenarannya adalah bahwa Israel “berperang melawan hewan manusia”.
Dua minggu kemudian, anggota Knesset, Tally Gotliv, menyatakan: “Tanpa kelaparan dan kehausan di antara penduduk Gaza… kami tidak akan bisa menyuap orang dengan makanan, minuman, obat-obatan untuk mendapatkan informasi.”
Selama beberapa bulan berikutnya, Israel tidak hanya menghalangi pengiriman bantuan kepada warga Palestina di Gaza, namun juga menyerang dan menghancurkan infrastruktur produksi pangan, termasuk ladang pertanian, toko roti, pabrik, dan gudang makanan.
Strategi yang disengaja ini, yang bertujuan untuk menundukkan dan mematahkan semangat rakyat Palestina, telah memakan banyak korban di Gaza – banyak di antaranya adalah bayi dan anak kecil. Namun hal ini juga mempunyai konsekuensi besar bagi warga Palestina di negara lain.
Sebagai seorang profesional kesehatan mental, saya telah menyaksikan secara langsung dampak psikologis dan fisik dari hukuman kolektif ini terhadap individu-individu di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki. Saya telah mengamati anak-anak muda Palestina yang mengembangkan hubungan yang rumit dengan makanan, tubuh mereka, dan identitas sosial dan nasional mereka sebagai respons terhadap kengerian yang mereka saksikan dan dengar setiap hari.
Penyembuhan penyakit ini memerlukan intervensi yang jauh lebih kompleks, yang tidak hanya mengatasi trauma individu namun juga trauma politik dan sejarah seluruh masyarakat.
Trauma yang dihasilkan secara politik dan sosial
Untuk memahami dampak kelaparan bersenjata, penting untuk mempertimbangkan kerangka sosial dan psikologis yang lebih luas di mana kelaparan tersebut terjadi. Ignacio Martín-Baró, seorang tokoh terkemuka dalam psikologi pembebasan, mendalilkan bahwa trauma dihasilkan secara sosial. Artinya, trauma bukan sekedar pengalaman individu, namun tertanam dan diperburuk oleh kondisi dan struktur sosial yang melingkupi individu tersebut.
Di Gaza, struktur yang menimbulkan trauma mencakup pengepungan yang sedang berlangsung, agresi genosida, dan perampasan sumber daya penting yang disengaja seperti makanan, air, dan obat-obatan. Trauma yang diakibatkannya diperparah oleh ingatan kolektif akan penderitaan selama Nakba (pembersihan etnis massal warga Palestina pada tahun 1947-8) dan berlanjutnya pengungsian serta penindasan sistemik terhadap pendudukan. Dalam lingkungan ini, trauma bukan sekedar pengalaman pribadi, namun merupakan realitas kolektif yang berakar secara sosial dan politik.
Meskipun warga Palestina di luar Gaza tidak secara langsung mengalami kekerasan genosida yang dilakukan Israel, mereka setiap hari dihadapkan pada gambaran dan cerita mengerikan tentang hal tersebut. Kelaparan yang tak henti-hentinya dan sistematis yang dialami warga Gaza sangat traumatis jika disaksikan.
Beberapa minggu setelah pernyataan Gallant, kekurangan pangan mulai dirasakan di Gaza. Pada bulan Januari, harga pangan melonjak, terutama di bagian utara Gaza, ketika seorang rekan saya mengatakan kepada saya bahwa dia membayar $200 untuk sebuah labu. Sekitar waktu ini, mulai muncul laporan tentang orang-orang Palestina yang terpaksa mencampurkan pakan ternak dan tepung untuk membuat roti. Pada bulan Februari, gambar pertama bayi dan anak-anak Palestina yang meninggal karena kekurangan gizi membanjiri media sosial.
Pada bulan Maret, UNICEF melaporkan bahwa 1 dari 3 anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi parah di Gaza utara. Pada bulan April, Oxfam memperkirakan rata-rata asupan makanan warga Palestina di Gaza utara tidak lebih dari 245 kalori per hari, atau hanya 12 persen dari kebutuhan harian. Pada saat ini, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa 32 warga Palestina, termasuk 28 anak-anak, telah terbunuh akibat kelaparan tersebut, meskipun jumlah kematian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.
Cerita juga beredar mengenai warga Palestina yang ditembak mati saat menunggu bantuan pangan didistribusikan, atau ditenggelamkan di laut saat mengejar bantuan makanan dari pemerintah yang mendukung perang Israel di Gaza.
Dalam sebuah surat yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada tanggal 22 April, Dr. Abdullah al-Jamal, satu-satunya psikiater yang tersisa di Gaza utara, menulis bahwa layanan kesehatan mental telah benar-benar hancur. Dia menambahkan: “Masalah terbesar saat ini di Gaza, terutama di wilayah utara, adalah kelaparan dan kurangnya keamanan. Polisi tidak dapat bertindak karena mereka langsung menjadi sasaran drone dan pesawat mata-mata dalam upaya mereka untuk menegakkan ketertiban. Kelompok bersenjata yang bekerja sama dengan pasukan Israel mengendalikan distribusi dan harga produk makanan dan obat-obatan yang memasuki Gaza sebagai bantuan, termasuk yang dijatuhkan dengan parasut. Beberapa bahan pangan, seperti tepung, harganya naik dua kali lipat, sehingga memperburuk krisis yang dialami penduduk di sini.”
Kasus klinis trauma kelaparan
Kelaparan Israel di Gaza berdampak psikologis dan fisik pada komunitas Palestina. Dalam praktik klinis saya, saya telah menemukan beberapa kasus di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki yang menggambarkan bagaimana trauma kelaparan di Gaza tercermin dalam kehidupan generasi muda Palestina yang jauh dari zona konflik. Inilah beberapa di antaranya.
Ali, remaja berusia 17 tahun dari Tepi Barat, mengalami perubahan perilaku makan dan kehilangan 8 kg (17 pon) dalam dua bulan setelah temannya ditahan oleh pasukan Israel. Meskipun berat badannya turun secara signifikan, dia membantah merasa sedih, dan bersikeras bahwa “penjara menjadikan manusia”. Namun, ia mampu mengungkapkan kemarahannya secara lebih terbuka terhadap kondisi di Gaza, dan pola tidurnya yang terganggu menunjukkan dampak psikologis yang besar. “Saya tidak bisa berhenti menyaksikan pemboman dan kelaparan di Gaza, saya merasa sangat tidak berdaya.” Hilangnya nafsu makan Ali merupakan wujud kemarahan dan kesedihan yang terinternalisasi dalam dirinya, mencerminkan trauma sosial yang lebih luas yang menyelimuti dirinya.
Salma, yang baru berusia 11 tahun, menyimpan makanan kaleng, botol air, dan kacang kering di kamarnya. Dia mengatakan dia “bersiap untuk genosida” di Tepi Barat. Ayah Salma melaporkan bahwa dia menjadi “histeris” ketika dia membawa pulang makanan mahal, seperti daging atau buah. Penurunan bertahap dalam asupan makanan dan penolakan makan, yang memburuk selama bulan Ramadhan, mengungkapkan rasa cemas dan bersalah yang mendalam atas kelaparan yang dialami anak-anak di Gaza. Kasus Salma menggambarkan bagaimana trauma kelaparan, bahkan ketika dialami secara tidak langsung, dapat mengubah hubungan anak-anak dengan makanan dan rasa aman mereka di dunia secara signifikan.
Layla, seorang gadis berusia 13 tahun, menderita ketidakmampuan misterius untuk makan, menggambarkan perasaan bahwa “sesuatu di tenggorokan menghentikan saya untuk makan; ada duri yang menghalangi jurangku.” Meskipun pemeriksaan medis ekstensif, tidak ditemukan penyebab fisik. Diskusi lebih lanjut mengungkapkan bahwa ayah Layla ditangkap oleh pasukan Israel dan dia tidak mendengar kabar apa pun sejak itu. Ketidakmampuan Layla untuk makan merupakan respons psikosomatis terhadap trauma penahanan ayahnya dan kesadarannya akan kelaparan, penyiksaan, dan kekerasan seksual yang menimpa tahanan politik Palestina. Dia juga sangat terpengaruh oleh laporan kelaparan dan kekerasan di Gaza, yang menyamakan penderitaan di Gaza dan nasib ayahnya yang tidak menentu, yang memperburuk gejala psikosomatisnya.
Riham, seorang gadis berusia 15 tahun, mengalami muntah-muntah berulang kali yang tidak disengaja dan rasa jijik yang mendalam terhadap makanan, terutama daging. Keluarganya memiliki riwayat obesitas dan gastrektomi, namun dia membantah adanya kekhawatiran mengenai citra tubuh. Dia mengaitkan muntahnya dengan gambar darah dan pemotongan orang-orang di Gaza yang dia lihat. Seiring berjalannya waktu, kebenciannya meluas pada makanan berbahan dasar tepung, dilatarbelakangi oleh ketakutan bahwa makanan tersebut dapat tercampur dengan pakan ternak. Meskipun dia mengerti bahwa hal ini tidak terjadi di tempat dia berada, perutnya menolak makanan ketika dia mencoba untuk makan.
Sebuah panggilan untuk bertindak
Kisah Ali, Salma, Layla, dan Riham bukanlah kasus klasik gangguan makan. Saya akan mengelompokkannya sebagai kasus gangguan makan akibat trauma politik dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks Gaza dan wilayah Palestina secara keseluruhan.
Anak-anak ini bukan hanya pasien dengan masalah psikologis yang unik. Mereka menderita akibat lingkungan traumatis yang diciptakan oleh kekerasan kolonial yang terus berlanjut, penggunaan senjata kelaparan, dan struktur politik yang melanggengkan kondisi ini.
Sebagai ahli kesehatan mental, tanggung jawab kita tidak hanya untuk mengatasi gejala yang dialami pasien, namun juga mengatasi akar politik dari trauma yang mereka alami. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan konteks sosiopolitik yang lebih luas di mana individu-individu tersebut tinggal.
Dukungan psikososial harus memberdayakan para penyintas, mengembalikan martabat dan menanggapi kebutuhan dasar sehingga mereka memahami keterkaitan antara kondisi penindasan dan kerentanan mereka serta merasa bahwa mereka tidak sendirian. Intervensi berbasis komunitas harus dilakukan dengan mempromosikan ruang aman bagi masyarakat untuk memproses emosi mereka, berpartisipasi dalam penyampaian cerita kolektif, dan membangun kembali rasa kendali.
Para profesional kesehatan mental di Palestina harus mengadopsi kerangka psikologi pembebasan, yang mengintegrasikan upaya terapeutik dengan dukungan komunitas, advokasi publik, dan intervensi struktural. Hal ini termasuk mengatasi ketidakadilan, menantang narasi yang menormalisasi kekerasan, dan berpartisipasi dalam upaya mengakhiri pengepungan dan pendudukan. Advokasi yang dilakukan oleh para profesional kesehatan mental memberikan validasi kepada pasien, mengurangi isolasi, dan meningkatkan harapan dengan menunjukkan solidaritas.
Hanya melalui pendekatan komprehensif seperti ini kita dapat berharap dapat menyembuhkan luka yang dialami individu dan masyarakat.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan posisi editorial Al Jazeera.