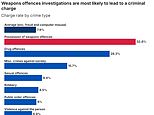Asmaa Elhardi biasa bangun pagi untuk berdoa. Saat itu hari Sabtu. Cahaya menerobos jendela apartemennya di Gaza utara.
Kemudian terdengar suara roket dan semuanya terbakar. Elcaldi dan suaminya melarikan diri hanya dengan membawa laptop dan dokumen penting.
Kemudian, “tanpa pemberitahuan apa pun, seluruh bangunan rata dengan tanah,” katanya dari barat daya Sydney, tempat dia tinggal sekarang. “Beberapa tetangga kami terbunuh.”
Elhardi telah berada di Australia sejak November.
“Saya masih merasakannya dengan sangat jelas,” katanya minggu ini, hampir setahun setelah meninggalkan tanah airnya. “Saya mengalami trauma semacam ini di tubuh saya dan saya merasa trauma itu bisa terjadi kapan saja.”
Berada di Sydney bisa jadi “lebih sulit daripada berada di Gaza”, katanya. Di sana, setidaknya “menonton genosida bersama keluarga dan teman-teman tahu bahwa mereka aman.”
“Saat Anda berada di negara lain, benua lain, pikiran Anda bisa menipu Anda, kekhawatiran Anda bisa dilebih-lebihkan, dan Anda bisa menjadi gila.”
Mahkamah Internasional mengatakan “masuk akal” bahwa Israel telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida. Pemerintah Israel bersikeras bahwa operasi militer tersebut merupakan respons yang sah terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan menolak klaim genosida sebagai “salah” dan “keterlaluan.”
Pada tanggal 7 Oktober, militan membunuh sekitar 1.200 orang di Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Dari 250 orang yang diculik oleh Hamas pada hari itu, separuhnya dibebaskan selama gencatan senjata singkat pada bulan November, dan separuh lainnya diyakini tewas.
Lebih dari 41.000 orang telah tewas di Gaza sejak serangan militer Israel dimulai, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, kata pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan hampir 2 juta warga Palestina mengungsi.
“Saya merasa seperti saya meninggalkan semua orang.”
Elcaldi pertama kali pindah ke Sydney pada April 2023 dengan beasiswa untuk belajar gelar master kebijakan publik di University of Sydney.
Dia mengunjungi Gaza pada Agustus lalu dan dijadwalkan kembali ke Sydney pada awal tahun 2024, “tetapi kemudian perang terjadi”.
Dia dan suaminya melarikan diri ke Rafah seminggu kemudian. Secara terpisah, keluarganya meninggalkan rumah mereka di Gaza utara enam minggu kemudian.
“Alhamdulillah mereka berhasil,” kata Elhardi. “Mereka berlarian di jalan dengan suara tembakan di atasnya.”
Pada bulan November, dia adalah “salah satu orang paling beruntung” yang dievakuasi oleh Departemen Luar Negeri Australia. Namun nama suaminya tidak ada dalam daftar.
“Saat saya melangkah keluar dari perempatan Rafah, hati saya serasa mau hancur,” kata Elhardi.
“Saya merasa seperti saya meninggalkan mereka semua dan menyelamatkan diri saya sendiri. Saya merasa sangat bersalah dan malu hingga saya menangis sampai tiba di hotel di bandara Kairo.”
“Aku kehilangan keinginan untuk hidup”
Elhardi yang saat ini sedang dalam visa pelajar telah kembali melanjutkan studinya. Dan suaminya tiba di Sydney.
Dia membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, dan belajar. Al Jazeera selalu tampil di TV dan dia begadang untuk menghubungi keluarganya.
“Kami aman, tapi keluarga kami sudah kembali ke Gaza. Tidak ada bantuan untuk kami.”
Ibu dan dua saudara laki-lakinya dievakuasi ke Turki, namun ayahnya tetap di Gaza bersama paman, bibi, sepupu, dan mertuanya.
“Terkadang koneksinya sangat buruk sehingga kami tidak bisa menghubunginya,” kata Elhardi tentang ayahnya.
“Aku khawatir dia dalam bahaya. Kita tidak bisa berumah tangga, kita tidak bisa menjalani kehidupan yang waras dan normal. Kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan buta.”
Elhardi mengatakan bagian tersulitnya adalah kehilangan sesuatu yang “tidak ada lagi”.
“Saya terus mengalami kilas balik pada waktu yang sangat acak,” katanya. “Ada kekosongan di hati saya dan saya tidak bisa mengisinya. Saya tidak ingin bisa bersosialisasi atau turun ke jalan dan melihat orang-orang menjalani kehidupan normal, tetapi orang-orang saya sendiri menjalani kehidupan normal.” ketika aku bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melihat diriku sendiri, aku merasa seperti kehilangan keinginan untuk hidup.
Bagi Nesma Khalil al-Kazendar, mantan insinyur konstruksi di Gaza, melarikan diri adalah hal yang membingungkan dan menakutkan.
“Tak satu pun dari kami memahami apa yang terjadi, apa yang terjadi pada kami, apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.
Dia melarikan diri bersama suami dan dua putrinya, berusia 3 dan 5 tahun, dari rumah mereka di Kota Gaza ke rumah kerabatnya, lalu ke tempat penampungan di Khan Yunis, lalu ke Rafah. Mereka mengungsi di Kairo seminggu sebelum penyeberangan perbatasan ditutup.
“Rumah saya dibakar, kemudian dibom, dan rumah orang tua serta mertua saya dihancurkan,” kata Khalil Al Khazendar, dari Sydney, yang saat ini tinggal dengan visa bridge.
“Setiap hari lebih buruk dari hari sebelumnya, dan setiap hari kami menghadapi kemungkinan kehilangan nyawa.”
Khalil Al Khazendar dan keluarganya tiba di Australia pada Juni 2024.
dia sedang belajar bahasa inggris dan berlari tangan palestinausaha yang menjual dukkah. Dia mengatakan tetap sibuk membantu kesehatan mental Anda. Suatu hari nanti, dia berharap bisa bekerja sebagai insinyur arsitektur lagi.
“Kami berterima kasih kepada Australia karena telah membuka pintunya bagi kami dan menerima kami dalam keadaan sulit ini,” kata Khalil Al Khazendar.
“Tetapi perasaan saya sangat sedih karena saya melihat negara saya dan keluarga saya mengalami masa-masa terburuk sejak saat ini.”
Setelah setahun berperang, Khalil al-Khazendar berkata, “Saya hanya ingin pulang dan mencari keselamatan hari ini, bukan besok.”
“Saya ingin mendapatkan kembali rasa aman yang tidak mungkin terjadi saat Anda jauh dari rumah, rumah, keluarga, teman, dan pekerjaan.”
“Semua orang di sini melakukan apa yang mereka bisa.”
Beban emosional menyaksikan perang berada di pundak komunitas Palestina dan diaspora yang baru tiba di Australia.
Lamia Sultan, seorang pengacara Palestina-Australia dan pemimpin komunitas Sydney, kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana komunitasnya bertahan selama 12 bulan terakhir.
Banyak dari diaspora tersebut adalah imigran generasi pertama dan kedua yang anak-anaknya lahir di Australia namun memiliki ikatan yang erat dengan Palestina.
Mereka hanya bisa menyaksikan Israel terus melakukan penembakan terhadap Gaza.
“Anda merasa lelah, Anda merasa bersalah, Anda merasa frustrasi, Anda merasa marah…keputusasaan bahkan lebih dalam lagi,” katanya.
“Setiap hari, terkadang setiap jam, kami menerima pesan dan telepon dari kerabat dan teman keluarga yang meminta bantuan. Semua orang di sini melakukan yang terbaik yang mereka bisa dalam batasan yang ketat, tapi… Harganya mahal.”
Menurut Sultan, rasa bersalah menentukan emosi. “Dari saat kita membuka mata hingga tertidur, kita terjebak dalam pemikiran ‘kenapa kita?’ tidak bisakah kita melakukan itu? Rasa bersalah itu menggerogoti komunitas kita.”
“Ini traumatis dalam banyak hal.”
Sultan mengatakan diaspora Palestina di Australia sering mengabaikan berita arus utama agar tetap mendapat informasi.
Sebaliknya, mereka menonton video langsung yang dikirim langsung dari Gaza atau dibagikan di grup WhatsApp. Mereka melihat kematian dan kehancuran terjadi.
Penulis dan akademisi Randa Abdelfattah mengatakan warga Palestina di Australia menyaksikan “dehumanisasi” terhadap orang-orang yang mereka cintai, dan hal ini menggerakkan komunitas tersebut.
“Kami telah menyadari bahwa dehumanisasi rakyat Palestina telah selesai,” katanya.
Kemarahan atas tanggapan pemerintah Australia terhadap konflik tersebut telah memicu protes mingguan di Sydney dan Melbourne.
Abdel Fattah mengatakan protes yang sedang berlangsung telah memungkinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka dan menunjukkan solidaritas meskipun ada upaya untuk menutup protes tersebut.
Namun orang-orang menjadi trauma karena menyaksikan perang dari dekat, seringkali karena rasa tanggung jawab.
“Sungguh traumatis melihat adegan horor dan pembantaian ini menjadi hal biasa,” kata Abdel-Fattah.
“Hal ini menimbulkan trauma di banyak tingkatan dan telah mengubah cara orang berinteraksi di tempat kerja, di lingkaran sosial, dan di komunitas.
“Kami menyaksikan bayi-bayi dikuburkan saat istirahat makan siang dan kemudian diharapkan untuk terus bertugas seolah-olah semuanya normal atau tidak terjadi apa-apa. Dan kami terus bertanya pada diri sendiri: ‘Mengapa dunia tidak berhenti setelah melihat ini?’
“Mereka bisa membangun tenda di atas reruntuhan rumah.”
Elhardi mengatakan tahun lalu mengingatkannya pada tahun 1948, ketika “seluruh tanah dicuri dan orang tidak bisa kembali ke rumah mereka.”
Warga Palestina menyebut pelarian, pengusiran, dan pencabutan tanah mereka sebagai bencana, atau Nakba.
Namun Elhardi mengatakan perang tersebut jauh lebih buruk. Jumlah kerusakan, jenis senjata, ukuran bom, dan intensitasnya.
Dia berharap untuk kembali ke Gaza suatu hari nanti, namun khawatir bahwa kehidupan di utara akan menjadi mustahil.
“Saya harap kecurigaan saya salah, karena… 1,5 juta orang yang tinggal di daerah yang sangat kecil di Selatan adalah tindakan yang tidak manusiawi dan saya harus kembali ke kampung halaman saya.
“Mereka bisa saja membangun tenda di atas puing-puing rumah, tapi setidaknya mereka akan kembali ke daratan.”
Khalil Al Khazendar berkata: “Satu-satunya harapan saya adalah dapat kembali ke rumah ketika keadaan sudah aman dan dibangun kembali, meskipun itu berarti saya tidak dapat kembali ke rumah saya, keluarga saya, atau teman-teman saya.”