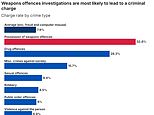FSepak bola adalah salah satu olahraga paling penuh kekerasan di dunia, baik daya tariknya maupun kekurangannya. Sebagai pemain, kami sangat menyadari risiko yang kami ambil setiap kali kami melangkah ke lapangan. Jika tidak, sering kali hal tersebut merupakan ketidaktahuan, sebuah keputusan sadar untuk menerima kebebasan sembrono yang dituntut oleh olahraga. Saya tidak tahu satu pun rekan setim saya di NFL atau karier kuliah saya yang tidak menderita sakit setiap hari selama hari-hari mereka bermain. Namun rasa sakit itu seringkali membawa kembali kenangan akan momen-momen berharga: persahabatan di ruang ganti, perjuangan di ruang angkat beban, dan pertarungan di lapangan. Di NFL, cedera ini terasa seperti medali kehormatan, bukti bertahan dalam permainan yang benar-benar dapat dipahami oleh mereka yang belum pernah bermain. Meski menderita, kebanyakan dari kita terus memainkan permainan yang kita sukai selama kita bisa, menerima konsekuensi dari pilihan hidup kita. Hanya sedikit orang yang menyesalinya, tetapi ada pula yang menyesalinya. Dan sayangnya, beberapa orang meninggal terlalu cepat karenanya. Namun apa yang terjadi jika risikonya lebih besar daripada imbalannya?
Perdebatan baru-baru ini mengenai kesehatan gelandang Miami Dolphins Tua Tagovailoa sekali lagi memulai perdebatan umum tentang kapan waktunya bagi seorang pemain untuk pergi. Setelah menderita gegar otak ketiga dalam dua tahun, banyak orang di dunia sepak bola mendesak Tua untuk pensiun dan “menghentikan tindakan”. orang-orang menunjukkannya Dia sudah mendapatkan $73 juta – Cukup untuk menghidupi pemain berusia 26 tahun dan keluarganya selama sisa hidupnya. Mengapa mempertaruhkan kesehatan Anda untuk pekerjaan yang berpotensi mematikan? Namun menjauh bukanlah pilihan yang mudah. Ini adalah perhitungan yang sangat pribadi yang melampaui perhitungan fisik.
Jika Anda hanya fokus pada kesehatan dan uang, Anda tidak akan melihat gambaran keseluruhannya. Pemain mengorbankan lebih dari sekedar tubuh mereka untuk bertahan dalam permainan. Kita juga menyerahkan sebagian dari kemanusiaan dan identitas kita. Kita diajari sejak usia muda bahwa kesuksesan dalam olahraga mengharuskan kita melakukan pengorbanan besar, seperti melepaskan keterlibatan sosial, hubungan, dan hobi demi kebaikan tim. Meskipun menempatkan tubuh kita dalam risiko adalah hal yang penting, hal ini sering kali bukanlah kekhawatiran kita. Seiring waktu, gaya hidup ini merusak kesehatan mental kita dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Kenyataannya adalah kita sebagai pemain terus-menerus mengalami kemunduran dan pikiran kita terpengaruh dengan cara yang tidak dapat kita kendalikan.
Saya mengetahui perjuangan ini secara langsung. Pada tahun 2019, saya menjadi pemain NFL pertama yang menyatakan diri sebagai biseksual, sebuah keputusan yang sangat membebani saya selama bertahun-tahun. Identitas saya adalah sesuatu yang harus saya tekan agar bisa masuk ke dalam pola kaku yang dituntut sepakbola. Ketegangannya bukan hanya tentang seksualitas saya. Bermain di era Colin Kaepernick, saya harus memilih di setiap pertandingan antara berlutut untuk memprotes ketidakadilan sosial dan membela titik lemah dalam skuad. Bagi banyak pemain, rasa takut dicap sebagai “pemain yang mengganggu” membuat mereka tetap diam dan menyembunyikan jati diri mereka agar tidak membahayakan karier mereka. Tekanan-tekanan ini menambah besarnya pengorbanan yang telah kita lakukan dan mengikis sebagian dari diri kita.
Jadi ketika masyarakat mendesak Pak Tua untuk pergi, mereka tidak hanya meminta masyarakat mempertimbangkan kesehatannya. Mereka memintanya untuk menghadapi semua arti sepak bola baginya. Apakah Anda akan menyerah pada olahraga yang telah Anda tinggalkan dalam banyak hal lainnya? Hal ini bukan sekedar untuk menghindari cedera lebih lanjut. Ini tentang bergulat dengan apa arti menjauh dari permainan bagi perasaan diri Anda.
Tua sekarang harus memutuskan apakah akan terus bermain atau pergi. Bagi orang luar, ini mungkin tampak sederhana, namun jauh lebih rumit. Berbeda dengan kembalinya Tom Brady dari masa pensiunnya, kepergian Tua adalah tanda bahwa ia cukup sehat secara mental dan kognitif untuk memainkan posisi paling penting dalam sepakbola, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi dunia. Ini adalah langkah yang tidak dapat diubah dan membebani mental.
Bagi banyak dari kita, sepak bola telah menjadi lebih dari sekedar pekerjaan. Itu identitas kami. Kita telah menginvestasikan segalanya di dalamnya: waktu kita, masa muda kita, kesehatan kita, dan bahkan kesadaran diri kita. Menjauh berarti kehilangan sebagian dari diri kita. Pergi mungkin berarti kehidupan yang lebih aman, tapi itu juga berarti menghadapi masa depan yang tidak pasti dan kemungkinan bahwa permainan ini telah mengambil lebih banyak dari kita daripada yang bisa kita akui. Meski lebih aman, siapa bilang hidup tanpa game lebih memuaskan? Apakah ini benar-benar sebuah pilihan?
Ketika saya masih menjadi pemain di Purdue, Mike Alstott yang hebat kembali ke almamaternya untuk berbicara kepada tim dan berbagi kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah. Dikenal sebagai salah satu pelari paling sengit baik di level perguruan tinggi maupun profesional, Alstott mewujudkan mentalitas seorang jagoan, pemain yang membutuhkan waktu lama untuk terjatuh dan tidak pernah terpuruk dalam waktu lama. Dia adalah tipe atlet yang tidak pernah tahu kapan cukup sudah cukup. Dia memberi kami banyak nasihat berharga hari itu, tapi ada satu kata yang melekat di benak saya. “Setiap atlet meninggal dua kali. Sekali di akhir kariernya dan sekali di akhir hidupnya.”
Kata-katanya tidak pernah terasa lebih benar daripada tindakan kedua atau ketiga dalam hidupnya, jauh dari sepak bola dan berduka atas kehilangannya sebagai pesepakbola. Saya melihatnya pada mantan rekan satu tim saya, beberapa di antaranya masih berduka atas kematian pertama mereka, bertahun-tahun setelah mereka meninggalkan permainan. Ketika saya melihat situasi Tua, saya berpikir: Jika Anda bisa memilih untuk mati terlebih dahulu, bukan? Atau akankah kamu bertarung sekuat tenaga dan tetap hidup?
Meskipun curahan keprihatinan terhadap Tua cukup membesarkan hati, memandang keputusannya hanya sebagai salah satu tanggung jawab pribadi tidak memperhitungkan konflik internal mendalam yang dihadapi sang pemain. Menjauh bukan hanya tentang menghindari cedera lebih lanjut. Ini tentang menghadapi kenyataan hidup tanpa sepak bola. Hal ini memaksa para atlet, seringkali di usia muda, untuk bertanya, “Apa gunanya hidup saya tanpa olahraga ini?” Apakah saya akan utuh tanpa bagian diri saya yang ini?
Namun penting juga untuk menyadari bahwa meninggalkan sepak bola dapat membuka pintu menuju awal yang baru. Beberapa pemain menemukan kepuasan dalam karier baru, advokasi, atau pertumbuhan pribadi. Meskipun jalur ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih sehat dan aman, transisi ini disertai dengan ketidakpastian dan gejolak emosi yang semakin memperumit pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, pilihan untuk berhenti dari sepak bola adalah pilihan yang sangat pribadi, ditentukan oleh faktor-faktor yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang pernah menjalaninya. Namun, cedera otak menempati bidang yang kompleks dan memerlukan keputusan yang sulit. Kisah Tua menjadi pengingat bahwa pengorbanan para atlet terhadap olahraga ini tidak hanya diukur dari gegar otak dan patah tulang. Itu diukur dari diri kita sendiri yang kita serahkan untuk memainkan permainan yang kita sukai. Dan terkadang bagian tersulitnya adalah memutuskan kapan cukup sudah cukup.
RK Russell adalah mantan pemain NFL yang bermain untuk Dallas Cowboys dan Tampa Bay Buccaneers.
Apakah Anda mempunyai pendapat tentang masalah yang diangkat dalam artikel ini? Klik di sini jika Anda ingin mengirimkan jawaban Anda hingga 300 kata melalui email untuk dipertimbangkan untuk dipublikasikan di bagian email kami.