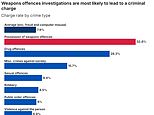Maputo, Mozambik – Pada jam 7 malam tanggal 4 November, jalanan Maputo menjadi sunyi senyap.
Transportasi umum lumpuh, menyusul seruan penutupan dari pemimpin oposisi Venâncio Mondlane.
Kemudian, suara berisik mulai terdengar. Penghuni gedung pencakar langit yang kaya dan blok apartemen di pusat kota bergabung dalam protes kekerasan yang terkoordinasi.
Dikenal sebagai “panelaco”, bentuk protes ini muncul sebagai cara yang ampuh untuk mengungkapkan rasa frustrasi atas hasil pemilu yang diperebutkan di Mozambik, sehingga memungkinkan warga untuk mengekspresikan perbedaan pendapat mereka tanpa menghadapi risiko pembalasan polisi. Kebisingan dan dentang bergema di cakrawala kota, menandai awal dari apa yang kemudian menjadi ekspresi frustrasi di malam hari, menyatukan penduduk dari berbagai divisi kelas.
Sejak pemilu 9 Oktober, deklarasi calon presiden dari Front Pembebasan Mozambik (Frelimo), Daniel Chapo, sebagai pemenang, telah memicu ketidakpuasan yang mendalam. Menurut Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE), Chapo memperoleh 71 persen suara dan Mondlane, kandidat independen, memperoleh 20 persen.
Namun, CNE pun mengakui adanya “beberapa penyimpangan”, yang menyebabkan Dewan Konstitusi meninjau kembali integritas pemilu.
Mondlane secara terbuka menolak hasilnya dan menyatakan dirinya sebagai pemenang yang sah. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 Oktober, pengacaranya Elvino Dias dibunuh, yang semakin meningkatkan kemarahan publik atas hasil pemilu, yang tidak dipercaya oleh banyak pemilih. Dias, tokoh sentral dalam tim hukum yang menggugat hasil resmi, sedang mempersiapkan kasus dugaan penipuan pemilih.
‘Suara yang tak bersuara’
Pada minggu-minggu berikutnya, Maputo menyaksikan serangkaian protes – demonstrasi perbedaan pendapat dalam semalam, tetapi juga seruan dari Mondlane yang mendesak para pengunjuk rasa untuk menutup situs-situs penting secara ekonomi, dari Maputo hingga ibu kota provinsi, pelabuhan dan pos perbatasan utama.
Para pekerja didorong untuk tidak bekerja, bisnis ditutup, dan orang-orang berkumpul untuk melakukan protes di kota-kota di seluruh negeri.
Seruan untuk memperketat lockdown telah menjadi hal yang mematikan di beberapa wilayah. LSM-LSM melaporkan bahwa sedikitnya 30 orang telah tewas sejak protes dimulai, termasuk dalam bentrokan yang disertai kekerasan dengan polisi.
Kerusuhan tersebut berdampak pada perdagangan regional, khususnya di pos perbatasan Lebombo dengan Afrika Selatan, yang ditutup sementara karena demonstrasi di kota terdekat, Ressano Garcia, sehingga memotong jalur penting bagi barang dan penumpang.
Mahasiswa teknik lingkungan Henrique Amilcar Calioio bergabung dalam protes di Maputo, di mana para pemuda meneriakkan “kekuatan untuk rakyat” dalam bahasa Portugis dan ditanggapi dengan gas air mata dari polisi.
“Meski tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan, kami terpaksa membubarkan diri,” ujarnya.
Calioio kemudian bergabung dalam protes malam hari dan memukul panci dan wajan sebagai cara untuk berteriak menentang apa yang disebutnya sebagai pemerintahan yang menindas.
“Sungguh menginspirasi mendengar orang-orang berkumpul untuk tujuan yang lebih besar,” katanya kepada Al Jazeera tentang protes panelaco. Dia mengatakan, memukul-mukul pot melambangkan “suara mereka yang tidak bersuara.”
Suatu malam, selama penggerebekan ganja yang terkoordinasi, kendaraan polisi melewati gedung tempat Calioio tinggal dan menyemprotkan gas air mata ke rumah-rumah, termasuk rumah Calioio, sehingga dia sangat kesakitan.
“Sangat mengejutkan bahwa bahkan di rumah kami, kami dilarang melakukan protes,” katanya.
‘Semua orang melakukan apa yang dikatakan Mondlane’
Shenaaz Jamal, seorang guru di Maputo, menuduh polisi “sangat, sangat keras”.
Dia menggambarkan perjalanannya sehari-hari antara rumah dan tempat kerja di bawah bayang-bayang kendaraan militer dan truk polisi yang diparkir di sepanjang jalan raya utama kota.
Pada hari-hari ketika para pengunjuk rasa mengindahkan seruan Mondlane untuk penutupan sekolah secara nasional, dia terpaksa mengajar secara online, meskipun hal ini merupakan tantangan karena pemadaman internet dan media sosial yang dilakukan pemerintah secara berkala. Sinyal telepon juga terputus-putus.
“Hari-hari sebelumnya terjadi kekacauan,” kenangnya. “Saya bisa mendengar suara tembakan. Itu gila. Dan yang membuatku frustasi adalah kami bahkan tidak bisa berkomunikasi. Aku tidak bisa menggunakan ponselku untuk menelepon siapa pun. Kamu tidak bisa memberi tahu keluargamu bahwa kamu baik-baik saja.”
Jamal mengatakan protes dan tanggapan masyarakat Mozambik – terutama kepatuhan masyarakat terhadap seruan Mondlane untuk penutupan nasional – adalah bukti bahwa hasil pemilu formal diragukan.
“Semua orang melakukan apa yang dikatakan Mondlane,” katanya.
“Pertanyaan yang ada di bibir semua orang adalah: jika dia hanya mendapat 20 persen dan Frelimo menang dengan 70 persen, bagaimana semua orang mengikuti apa yang dia katakan?”
‘Kekecewaan yang kuat’
Sam Jones, peneliti senior di World Development Economic Research Institute, yang merupakan bagian dari Universitas PBB, yakin bahwa protes ini memiliki akar sosio-ekonomi yang lebih dalam, lebih dari sekadar pemilu tunggal.
“Mozambik dilanda stagnasi ekonomi dan masyarakatnya frustrasi,” jelas Jones.
“Ada perasaan kumulatif bahwa negara ini tidak berada di jalur yang benar. Selama 10 tahun kita hampir tidak mengalami pertumbuhan ekonomi dan terdapat kekecewaan yang kuat terhadap elit penguasa. Mondlane telah berhasil menjalin hubungan efektif dengan kaum muda, memobilisasi mereka dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya.”
Sebagai tanggapan, Bernardino Rafael, komandan Kepolisian Republik Mozambik, mengutuk protes tersebut sebagai “terorisme perkotaan”, dan menyatakan bahwa niat mereka adalah untuk mengganggu stabilitas tatanan konstitusional.
Namun, banyak yang menganggap respons pemerintah terlalu agresif. Bagi Jamal, adegan kerusuhan merupakan sebuah keakraban yang menghantui. Orang tuanya meninggalkan Mozambik lebih dari 30 tahun yang lalu untuk menghindari perang saudara, dan sekarang dia khawatir kekerasan serupa akan kembali terjadi di kampung halamannya.
Jones mengatakan tanggapan negara hanya memperburuk konflik.
“Polisi merespons dengan keras dengan gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam. Dalam banyak kasus, kekerasan diakibatkan oleh tindakan brutal aparat keamanan, yang hanya memperdalam kebencian di kalangan pengunjuk rasa.”
Kekurangan pangan
Kerusuhan yang berkepanjangan mulai mempengaruhi pasokan pangan di Maputo, negara yang sangat bergantung pada impor dari Afrika Selatan.
“Ada kekhawatiran seputar kekurangan pangan karena wilayah perbatasan telah beberapa kali mengalami protes bahkan penutupan perbatasan,” kata Jones.
Siphiwe Nyanda, komisaris tinggi Afrika Selatan di Mozambik, mengakui ketegangan lintas batas, dan mencatat bahwa supermarket di Maputo mengalami kekurangan pasokan secara langsung karena gangguan rantai pasokan terkait protes tersebut.
“Hal ini menyebabkan masalah serius bagi Mozambik dan Afrika Selatan, terutama kota-kota perbatasan yang bergantung pada perdagangan,” katanya, seraya menambahkan bahwa perbatasan Libombo, salah satu perbatasan tersibuk di kawasan ini, berfungsi sebagai jalur perdagangan yang penting.
“Protes ini telah menciptakan efek riak yang tidak hanya mempengaruhi perekonomian lokal, tetapi juga para komuter dan kehidupan sehari-hari di tempat-tempat seperti (kota perbatasan Afrika Selatan) Komatipoort, yang bergantung pada pekerja dan bisnis Mozambik.”
Krisis yang sedang berlangsung telah menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 10 juta rand ($550.000) per hari bagi Afrika Selatan, menurut Gavin Kelly, CEO South African Road Freight Association.
Di Mozambik, lebih dari 150 toko dirusak, dengan kerugian diperkirakan mencapai US$369 juta, yang semakin memperburuk gejolak ekonomi.
Kini Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, blok regional beranggotakan 16 negara, telah menjadwalkan pertemuan darurat di Harare pada hari Sabtu untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Namun, saat kembali ke Maputo, Jones yakin protes tersebut telah mencapai puncaknya – skala dan kegigihannya tidak biasa di Mozambik dan merupakan indikasi kemarahan yang tidak dapat dengan mudah dipadamkan oleh para politisi dan diplomat di negara dan wilayah tersebut. .
“Kami telah melihat protes pasca pemilu sebelumnya, namun jarang terjadi protes yang berkelanjutan. Biasanya setelah beberapa hari orang menjadi lelah, apalagi sepertinya tidak ada perubahan,” ujarnya.
“Kali ini, partisipasi lebih luas dan intens, tidak hanya mencerminkan keluhan pemilu namun juga ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap status quo.”