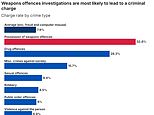Lebanon menghadapi ancaman yang sama destruktifnya dengan bom yang menghujani kota-kotanya: krisis pengungsian yang berisiko menghancurkan negara tersebut dari dalam. Komunitas-komunitas telah mencapai batas kemampuannya, dan perpecahan yang terjadi di masyarakat Lebanon semakin melebar dari hari ke hari. Jika hal ini terus berlanjut, ledakan yang terjadi bisa lebih dahsyat daripada perang itu sendiri.
Lebih satu juta orang meninggalkan rumah mereka dalam 72 jam pertama pemboman Israel. Eksodus ini berlangsung cepat dan kacau, menyebabkan keluarga-keluarga tersesat dan tidak yakin ke mana harus berpaling. Tidak butuh waktu lama untuk sebuah pola muncul – orang-orang mengungsi ke daerah yang “lebih aman” – namun disitulah perintah tersebut berakhir. Hanya tentang 190.000 dari sekitar 1,2 juta pengungsi menemukan jalan mereka ke tempat penampungan yang terorganisir. Mayoritas masyarakat kini tidak terlihat lagi, tinggal di akomodasi informal, menyewakan rumah dengan harga yang sangat mahal, tinggal di rumah-rumah kosong dan gedung-gedung tinggi, atau berdesakan di rumah teman dan kerabat. Populasi yang tidak terlihat ini memperumit respons yang sudah kewalahan.
Pemerintah telah meluncurkan struktur dasar di tempat penampungan darurat dan mulai menunjuk titik fokus untuk mengelola distribusi bantuan. Masyarakat umum Lebanon telah menawarkan rumah dan kantor mereka, dan restoran membagikan makanan gratis. Namun solidaritas saja tidak cukup.
Ketakutan, ketidakpercayaan, dan meningkatnya ketegangan
Ketakutan dan ketidakpercayaan sektarian kini merusak tatanan sosial Lebanon yang rapuh dan mengancam stabilitasnya. Masyarakat di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Druze, khawatir bahwa menampung keluarga pengungsi dari wilayah yang terkait dengan Hizbullah akan menyeret mereka ke dalam konflik, semakin ragu untuk membuka pintu bagi mereka. Laporan baru-baru ini mengenai Israel yang menargetkan properti sewaan yang menampung para pengungsi telah memperkuat ketakutan ini, sehingga semakin melemahkan tindakan untuk menampung pengungsi.
Ketakutan ini lebih besar dari sekedar reaksi individu; hal ini juga mendorong pengambilan kebijakan. Beberapa kota telah menyatakan bahwa menampung para pengungsi internal (IDP) terlalu berbahaya karena khawatir Israel akan menargetkan mereka. Memang benar, awal pekan ini, serangan Israel meratakan sebuah bangunan tiga lantai di desa Aitou yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, menewaskan sedikitnya 22 orang, di antaranya 12 wanita dan dua anak-anak. Tempat tinggal tersebut baru-baru ini disewakan kepada sebuah keluarga yang mengungsi dari wilayah selatan, dan PBB telah menyerukan penyelidikan.
Pergeseran pola pengungsian ini mengancam akan merusak keseimbangan sektarian Lebanon yang rapuh, dan kelompok yang paling rentan – yaitu para pengungsi itu sendiri – adalah pihak yang akan menanggung akibatnya.
Oportunisme mengipasi api
Respons pemerintah tidak merata. Rencana darurat memberikan kerangka kerja yang sederhana, namun kenyataan di lapangan sangat memprihatinkan. Solusi seperti pembangunan rumah prefabrikasi dan penggunaan kembali gedung-gedung milik pemerintah, termasuk gedung-gedung yang berada di bawah kendali bank sentral Lebanon, telah diusulkan namun sebagian besar masih berupa perbincangan. Kelompok kepentingan, khususnya di sektor perbankan dan politisi, enggan mempertimbangkan bangunan apa pun selain sekolah. Mereka mengincar properti bank sentral (bukan aset mereka sendiri) untuk memberikan kompensasi kepada para deposan yang kehilangan tabungannya akibat krisis keuangan yang mereka timbulkan. Oportunisme semacam ini merupakan bentuk pengabaian terhadap masyarakat yang sudah mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun, dan kini diperparah oleh konflik terburuk sejak Perang Saudara tahun 1975-1990.
Daripada ragu-ragu, tindakan harus diambil dalam jangka pendek untuk memperluas kapasitas tempat penampungan umum dan meringankan beban sekolah dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia – tempat penampungan prefabrikasi, gedung pemerintah, bantuan tunai, dan apa pun yang dapat dimobilisasi.
Unit Manajemen Risiko Bencana (DRM) milik pemerintah telah mencapai kemajuan dalam melatih masyarakat untuk menjadi titik fokus shelter dan mengelola shelter kolektif, namun populasi yang tidak terlihat – sebagian besar di luar sistem formal yang tidak dapat memanfaatkan shelter ini – tidak dapat diabaikan. Jika respons Lebanon tidak memperhitungkan orang-orang ini, maka negara tersebut akan runtuh ketika uang negara atau keramahtamahan yang mereka andalkan habis—keduanya akan berkurang dengan cepat.
Dalam jangka menengah, skema sewa yang didukung pemerintah dengan pengendalian sewa perlu diterapkan untuk melindungi tuan tanah dan keluarga pengungsi. Skema ini harus bertujuan untuk beralih dari solusi kepemilikan pribadi ke solusi perumahan umum dalam waktu secepat mungkin, sehingga pemerintah mempunyai waktu untuk menggunakan kembali properti milik negara, menampung para pengungsi dan, pada akhirnya, mengembalikan anak-anak ke sekolah.
Menghindari konflik sipil
Jika krisis ini memperjelas hal ini, maka kebijakan perumahan jangka panjang Lebanon memerlukan perombakan besar-besaran. Pemerintah harus mengatasi masalah struktural di pasar properti dengan mengatur harga dan mengenakan pajak pada properti kosong diperkirakan 20 persen dari stok perumahan. Lebanon tidak bisa membiarkan spekulasi terus menerus membuat perumahan tidak terjangkau oleh mereka yang paling membutuhkan. Para pengungsi – baik warga Lebanon, Suriah, atau kelompok marjinal lainnya – harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggusuran paksa, dan pemerintah harus menjamin akses terhadap layanan dasar seperti air, listrik, dan sanitasi.
Dengan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam strategi perumahan darurat, Lebanon dapat mulai mengatasi keretakan baru dalam tatanan sosialnya. Alternatifnya adalah membiarkan rasa takut, kecurigaan, dan kekuatan pasar mendominasi, sehingga menciptakan kembali kondisi yang memicu terjerumusnya Lebanon ke dalam perang saudara beberapa dekade lalu.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.