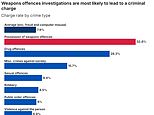THang Tun, 29, masih di tempat tidur ketika para pria datang untuk membawanya ke rumahnya di Yangon. “Dia tidak bisa mempersiapkan apa pun. Mereka hanya menyuruhnya membawa kartu identitas nasional, salinan pendaftaran sensus dan dua pakaian,” kenang saudara perempuannya, Khin Mei.
Sekelompok tentara dan pejabat setempat merekrut Tan Htun secara paksa ke dalam militer Myanmar. Dia akan dipaksa untuk berperang demi rezim militer yang sangat dibenci di negara tersebut dalam perang sengit melawan aktivis pro-demokrasi dan kelompok etnis bersenjata.
Pemerintahan militer Myanmar menerapkan wajib militer untuk pertama kalinya pada tahun ini, sebuah langkah yang memicu ketakutan di seluruh negeri.
Mereka yang mampu segera melarikan diri, menjual seluruh harta benda mereka dan berhutang untuk membiayai pelarian mereka. Antrean di luar kedutaan membentang berjam-jam, banyak di antaranya berada di wilayah yang dikuasai pemberontak di negara tersebut.
Mereka yang tetap tinggal di kota-kota yang dikuasai militer seperti Yangon membayar suap kepada pejabat setempat untuk menghindari wajib militer dan terus-menerus hidup dalam ketakutan.
Keluarga dari seluruh negeri mengatakan hal berikut. pengamat Bagaimana orang-orang tercinta diambil dari rumah mereka, dipaksa masuk dinas militer, atau dibawa keluar dari jalanan oleh tentara.
Dipercaya bahwa 25.000 orang telah dibawa ke kamp pelatihan sejak bulan April, ketika militer memulai proses wajib militer, yang diwajibkan bagi pria berusia 18 hingga 35 tahun pada bulan Februari, dan 5.000 di antaranya telah dikerahkan ke garis depan. .
Bagi militer yang menghadapi kekurangan tenaga kerja setelah serangkaian kekalahan dan pembelotan yang memalukan, undang-undang wajib militer bisa menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Lebih dari tiga tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, upaya sedang dilakukan untuk menghentikan kelompok bersenjata yang menentang pemerintahan negara tersebut dan kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah di sepanjang perbatasan negara untuk melakukan itu.
“Militer terus mengalami kekalahan,” kata Morgan Michaels, peneliti politik Asia Tenggara dan kebijakan luar negeri di Institut Internasional untuk Studi Strategis. “Jika kerugian ini terus berlanjut pada tingkat ini, maka hal ini tidak berkelanjutan.”
Kekalahan militer meningkat sejak Oktober tahun lalu, ketika koalisi yang dikenal sebagai Aliansi Persaudaraan melancarkan serangan mendadak di negara bagian Shan di utara. Militer sudah berjuang untuk mengendalikan kelompok-kelompok anti-junta (disebut Pasukan Pertahanan Rakyat) yang dibentuk oleh warga sipil yang menentang kediktatoran setelah kudeta, dan dalam banyak kasus oleh kelompok-kelompok yang lebih mapan yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan. Militer juga mendapat dukungan dari beberapa etnis bersenjata kelompok. .
Masuknya Aliansi Persaudaraan ke dalam konflik semakin memperluas angkatan bersenjata. Selama beberapa bulan berikutnya, ribuan personel militer, termasuk seluruh batalyon, dilaporkan telah menyerah.
Sedikit yang diketahui tentang pelatihan wajib militer. Banyak yang khawatir mereka akan digunakan sebagai umpan meriam atau pengangkut barang. Mereka sebenarnya adalah perisai manusia yang dikirim untuk membersihkan ranjau dan melindungi tentara dari tembakan.
Para prajurit meyakinkan keluarga Tan Tun bahwa mereka akan dikirim untuk pelatihan dan kemudian kembali ke Yangon untuk bekerja sebagai penjaga keamanan. “Bagi kami, sangat meyakinkan mendengarnya,” kata Khin May.
Tapi itu tidak benar. Sebaliknya, ia dikirim ke negara bagian Rakhine di perbatasan barat. Negara bagian Rakhine telah menjadi pusat pertempuran terburuk, di mana militer berusaha mati-matian menghentikan Tentara Arakan, yang merupakan anggota aliansi Ikhwanul Muslimin.
Tan Hu Tung menelepon keluarganya setiap kali dia mendapat sinyal telepon. Kakaknya mengingat setiap percakapan. Awalnya, ia ditempatkan sebagai satpam di kawasan pusat kota ibu kota provinsi, Sittwe. Dia kemudian memberi tahu mereka bahwa dia perlu naik kapal ke Maungdaw di negara bagian Rakhine utara, namun badai hebat telah membuatnya terdampar di tengah lautan, sehingga navigasi menjadi mustahil. “Kami kehabisan makanan dan terpaksa minum air hujan,” katanya.
Yang lainnya menghadapi nasib yang lebih buruk. Sebuah kapal angkatan laut militer diserang oleh drone, melukai banyak tentara. Tan Fu Tung memberitahunya bagaimana pasukannya dikirim untuk menyelamatkan mereka.
Pada akhir bulan Juli, Tan Tun menelepon saya lagi pada suatu malam dan mengatakan bahwa saya harus naik speedboat ke Maungdaw. “Itu adalah panggilan telepon terakhir yang dia lakukan kepada kami. Sejak saat itu, kami belum mendengar kabar lagi darinya,” katanya.
Militer telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud merekrut hingga 60.000 tentara pada akhir tahun ini, dan media rezim mengatakan bahwa ini adalah langkah untuk melenyapkan penentang junta yang dipandang sebagai teroris yang berupaya mengganggu stabilitas negara.
Militer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa mereka telah mengundang kelompok-kelompok “teroris” untuk menghentikan pertempuran dan menyelesaikan masalah ini secara politik melalui pemilihan umum. Proposal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diyakini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen terhadap stabilitas sekutu Tiongkok tersebut. Di kalangan masyarakat, hal ini secara luas dipandang sebagai delusi dan tidak jujur. Beberapa jam kemudian, militer melancarkan serangan udara di negara bagian Shan bagian utara. Kelompok-kelompok pendukung gerakan demokrasi ingin sepenuhnya mengecualikan militer dari politik, namun rezim militer sepertinya tidak akan menerima hal ini.
Setelah promosi buletin
Tan Hu Tun adalah satu dari ratusan ribu orang yang turun ke jalan menuntut kembalinya demokrasi setelah militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021. Militer menanggapi protes damai mereka dengan menembak, menahan, dan bahkan menyiksa dan membunuh mereka. Seseorang yang dicurigai menentang pemerintahan militer dan mendorong masyarakat untuk mengangkat senjata.
Konflik yang terjadi kemudian menjungkirbalikkan negara. Layanan dasar seperti layanan kesehatan telah runtuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan angka kemiskinan meroket. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada akhir tahun 2023, hampir separuh penduduk negara tersebut akan hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 1.590 kyat (sekitar 50 pence) per hari, naik dari 24,8% pada tahun 2017.
Wajib militer paksa, yang membuat generasi muda menjauhi negaranya, hanya memperburuk kesulitan ekonomi.
So Jung juga seorang pemuda yang diculik dari rumahnya. Dia mencari nafkah dengan mengantarkan makanan dengan sepeda dan menjadi satu-satunya pencari nafkah di rumah tempat dia tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dia dibawa ke kantor polisi karena menolak wajib militer, kemudian ke pusat interogasi dan kemudian ke pusat pelatihan di Negara Bagian Shan.
Orangtuanya dijanjikan dukungan, namun hal itu tidak pernah terwujud. Saya tidak bisa membayar sewa dan pemilik rumah mengusir saya.
Ibu Sou Jeong meninggal pada akhir Agustus. “Saya pikir dia meninggal karena tekanan emosional setelah tidak dapat menghubungi putranya,” kata Win Khanh, seorang teman dekatnya. “Setelah anak saya ditangkap, mereka jarang berbicara satu sama lain. Saya harus terus mengawasi mereka di malam hari selama sebulan karena saya khawatir mereka akan mencoba bunuh diri.”
Tuan Win Khanh sangat marah, katanya. “Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya hanya manusia. Saya tidak bisa melindungi diri dari senjata. Saya tidak ingin disiksa oleh tentara.”
Pada masa-masa awal wajib militer, beberapa orang setuju untuk wajib militer dengan imbalan insentif keuangan yang dikumpulkan oleh orang lain di lingkungan mereka.
Laporan-laporan mengatakan bahwa kini jauh lebih sedikit orang yang bersedia melakukan hal ini, dan akibatnya, militer melakukan lebih banyak penangkapan.
Di antara mereka adalah saudara laki-laki Tidar, 27 tahun, yang ditangkap bersama pekerja lainnya saat pulang kerja di ladang kacang pada bulan lalu. Hanya dua hari kemudian, mereka dikirim ke Taunggyi di Negara Bagian Shan.
“Sekarang saya bahkan takut untuk pergi ke hutan dekat desa saya,” kata Tidar. Seluruh desa putus asa. “Bukan hanya kakak dan keponakan saya, tapi semua wajib militer lainnya adalah sepupu dan kerabat saya. Keponakan saya punya istri yang sedang hamil,” imbuhnya.
Jika mereka mau berperang, ia berharap mereka akan melakukan lebih banyak lagi atas nama perlawanan terhadap rezim militer. “Kami tidak punya kebebasan lagi. Kami bekerja dalam ketakutan, bertanya-tanya bagaimana militer bisa tahu keberadaan kami,” kata Tidar.
Seperti adik Tan Fu Tung, dia tidak tahu apa-apa tentang nasib kakaknya. Menurut Khin May, masyarakat termiskin menjadi sasaran wajib militer, bukan anak-anak personel militer yang telah meninggalkan negaranya atau orang kaya.
Ibu Tan Hu Tun masih percaya bahwa dia masih hidup dan mungkin telah ditangkap dan ditahan oleh pasukan anti-junta. Dia menderita diabetes dan tekanan darah tinggi, dan kondisinya semakin memburuk sejak suaminya dibawa pergi pada bulan April. Dengan berlinang air mata, dia terus berdoa untuk keselamatannya.
“Kami ingin mengetahui secara pasti apakah saudara kami masih hidup atau sudah meninggal,” kata Khin Mei. “Jika dia meninggal, kami ingin tubuhnya kembali.”
Semua nama orang yang diwawancarai telah diubah