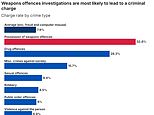Beirut, Lebanon – “Tidak ada telepon!” gonggongan seorang pria kekar saat dia melewati kami dengan skuternya. Saya berada di kota bekerja dengan koresponden Al Jazeera, Ali Hashem. Temannya dan sesama jurnalis, Ghaith Abdul-Ahad, yang bersama kami, baru saja mengambil gambar sebuah bangunan tua yang indah, terletak di antara etalase toko dan apartemen di jalan yang sibuk di Basta, pusat Beirut.
Meskipun pria tersebut jelas-jelas warga sipil – bukan pejabat apa pun – Ghaith dengan cepat mematuhi perintahnya. Dia meminta maaf dan meletakkan ponselnya, namun pria yang marah itu telah memutar skuternya dan mendekat, menuntut untuk melihat ponsel dan gambar yang menyinggung tersebut.
Ketegangan semacam ini lebih dari sekedar muncul di bawah permukaan kota ini. Beirut berada di ujung tanduk. Dalam sebulan terakhir, warga kota ini berulang kali mengalami peristiwa traumatis. Pertama, terjadi serangan pada pertengahan September ketika ribuan radio pager dan walkie-talkie milik komandan Hizbullah meledak di rumah-rumah dan tempat-tempat umum, menewaskan 32 orang dan menyebabkan ribuan orang terluka.
Hal ini diikuti oleh serangan udara yang tak terhitung jumlahnya terhadap apa yang diklaim pasukan Israel sebagai sasaran Hizbullah mulai tanggal 20 September, sebagian besar terfokus pada Dahiyeh di selatan kota, di sebelah bandara. Pada tanggal 27 September, pemimpin Hizbullah selama 32 tahun, Hassan Nasrallah, dipastikan tewas setelah Israel menjatuhkan 85 bom “penghancur bunker” di pemukiman selatan pinggiran kota.
Adegan pembunuhan yang nyata
Serangan tanggal 20 September menjerat banyak warga sipil tak berdosa, termasuk keluarga juru kamera Al Jazeera Ali Abbass yang tinggal di gedung yang berdekatan dengan serangan tersebut. Putranya, Mohammed, menggambarkan dirinya terlempar dari tempat tidurnya saat apartemennya tertutup debu – dan kemudian mendengar jeritan mengerikan dari orang-orang yang terluka. Ali segera memindahkan keluarganya ke hotel tempat staf Al Jazeera menginap, istrinya datang dengan gemetar, masih mengalami syok.
Sehari kemudian, unit hubungan media Hizbullah memberi wartawan tur mengenai upaya penghancuran dan pemulihan.
Koresponden Imran Khan dan saya mendapati diri kami menunggu di jalan berdebu tempat terjadinya pemogokan bersama jurnalis lokal dan kru TV, sebelum bergabung dengan beberapa stasiun penyiaran internasional Barat, untuk membuat keributan media besar-besaran.
Dahiyeh lebih tenang dari biasanya. Kemacetan berkurang namun masih banyak warga yang berjejer di jalan, sebagian untuk mengamati media; yang lain, termasuk Ali, kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan apa yang mereka bisa. Beberapa toko terpaksa tutup tetapi yang lain masih berusaha melanjutkan aktivitas seperti biasa.
Setelah beberapa jam menunggu, kami tiba-tiba diberi isyarat oleh petugas media Hizbullah untuk mendekat dan kami bergegas menuju lokasi ledakan, kamera-kamera mati-matian mencari posisi terbaik untuk mengamati pembantaian tersebut.
Pada awalnya, tidak sepenuhnya jelas – melalui kebisingan dan kekacauan para penggali, pekerja, dan puing-puing – apa yang sebenarnya kita lihat.

Bangunan di depan kami tampak tingginya sekitar tujuh lantai dan lebar 50 meter. Namun di sekeliling dasarnya terdapat sebuah kawah besar yang memperlihatkan fondasi kerangkanya. Ruang bawah tanahnya tampak hancur total, begitu pula lantai dasar dan dua atau tiga lantai di atasnya.
Anehnya, lantai yang lebih tinggi masih utuh, namun bangunan tersebut masih tampak cukup kokoh, meskipun terjadi kerusakan besar. Saya bertanya-tanya bagaimana ia masih bisa berdiri.
Komandan militer Hizbullah, Ibrahim Aqil, berada di ruang bawah tanah gedung ini dan Israel sekali lagi menggunakan amunisi yang kuat untuk membunuhnya, dan juga membunuh 30 warga sipil di dekatnya.
Segera setelah saya mulai memahami kejadian ini, para pejabat yang membawa kami ke sini meneriaki kami untuk melanjutkan.
Imran dan saya buru-buru mengambil laporan dan beberapa gambar yang terburu-buru ketika kamera saya berulang kali ditekan dengan marah oleh petugas media dan kami dibawa keluar dari blok, merasa dilecehkan dan bingung, kembali ke jalan sempit di luar. Beberapa rekan lokal saya kemudian memberi tahu saya bahwa perilaku kontradiktif terhadap pers seperti ini biasa terjadi di Lebanon.
‘Kamu orang Inggris’ – kebencian dan kemarahan
Di Beirut, kami menemukan bahwa upaya pengumpulan berita kami terus-menerus dirundung kesulitan.
Hal ini terjadi ketika kami meliput distribusi bantuan oleh UNICEF di tempat penampungan pengungsi di luar Beirut di pegunungan Bsous beberapa hari kemudian, pada tanggal 26 September.
Pada kesempatan ini, saya langsung dihentikan oleh seorang pejabat Hizbullah yang meminta untuk melihat akreditasi media saya, dan kemudian mencoba mencari-cari kesalahannya. Produser kami, Zeina, melakukan panggilan telepon dengan tergesa-gesa ke kontaknya dan, setelah beberapa menit yang cemas, pria itu mengalah dan mengizinkan kami melanjutkan.
Meskipun begitu, kami tetap tidak diperbolehkan memasuki tempat penampungan dan harus puas dengan pengambilan gambar di luar tempat terdapat beberapa pengungsi dari selatan Lebanon dan para sukarelawan menurunkan bantuan, air, kasur dan makanan.
Kami melihat banyak tatapan curiga dari beberapa orang yang jelas-jelas tidak puas, baik relawan maupun pengungsi, tidak senang melihat kru TV berusaha mengabadikan penderitaan mereka. Hal ini telah menjadi sebuah pola di Lebanon; mengatur untuk syuting di suatu tempat hanya untuk mengetahui bahwa begitu kami tiba, mereka yang bertanggung jawab telah berubah pikiran.

Ada juga kebencian. Seorang pemuda bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris yang sempurna: “Anda orang Inggris, mengapa Inggris mendukung Israel?”
Suasana tidak membaik ketika pejabat UNICEF muncul bersama kru TV Amerika.
Kotak-kotak bantuan yang tersegel disusun dengan hati-hati, ditumpuk di belakang petugas UNICEF saat mereka tersenyum dan berpose untuk sesi foto.
Namun perasaan permusuhan terus membayangi dan seorang pria dengan marah berteriak: “Kalian orang Barat memasok bom ke Israel dan yang bisa kalian berikan kepada kami hanyalah beberapa selimut?”
Senyuman UNICEF dengan cepat berubah menjadi ekspresi cemas. Ini bukanlah sambutan yang mereka harapkan. Dorsa Jabbari, koresponden kami, dengan bijak memutuskan bahwa tidak ada gunanya jika tetap tinggal dan kami kembali ke kantor kami di Beirut.
Sekembalinya kami, kami menyadari dengungan rendah yang terus-menerus seperti mesin pemotong rumput yang jahat. Mencari sumber kebisingan, kami menjulurkan leher, menatap ke atas hingga kami bisa melihat drone Israel berputar-putar di langit yang tak terbantahkan di atas.
Kontrol penuh Israel atas langit Beirut memungkinkan pesawat mereka berkeliaran dan menargetkan dengan bebas dan berulang kali. Kami telah kehilangan jejak jumlah pembunuhan terhadap para pemimpin dan komandan Hizbullah ketika drone tersebut bergerak dari Dahiyeh dan kadang-kadang menyimpang ke pusat kota Beirut.

Pada tanggal 11 Oktober, kami berangkat ke lokasi serangan lain pada malam sebelumnya di lingkungan Basta. Awan debu tebal menyelimuti jalan, menutupi mobil, trotoar, dan manusia seperti salju halus.
Ketika Ali Hashem dan saya semakin dekat ke pusat serangan, kami melihat mobil-mobil terlempar ke gedung-gedung, bahkan di atas mobil-mobil lain, dan di pusat gempa, yang ada hanya puing-puing berasap di bekas bangunan tersebut pernah berdiri.
Seorang penggali JCB menyekop segenggam logam dan beton yang bengkok, nyaris tidak menggores permukaan tumpukan besar kehancuran yang mungkin menjadi tempat terperangkapnya banyak orang.
Di segala penjuru, bangunan-bangunan di sekitarnya penuh dengan bekas luka, lubang-lubang raksasa menembus dinding, dan satu blok kini menyerupai rumah boneka yang mengerikan. Di dalam, kusen jendela, daun jendela, dan pintu pecah karena kekuatan ledakan, terlempar ke seluruh ruangan seperti proyektil mematikan.

‘Mereka mata-mata!’
Setelah mengamati kerusakan tersebut sambil berjalan kembali ke mobil kami dalam suasana hati yang muram, Ghaith mengambil gambar bangunan yang indah – sebuah tanda harapan di tengah kehancuran tersebut – yang membuat pria yang mengendarai skuter tersebut sangat marah.
Dia berbalik dan bergegas kembali ke arah kami dengan marah. “Berikan ponselmu!” dia menuntut saat kami mencoba menenangkannya.
Sebelum kami dapat menyerahkan teleponnya, dia meninju kepala Ghaith dengan keras – kekerasan brutal dan tiba-tiba yang tampaknya menggarisbawahi trauma yang telah dialami oleh lingkungan ini.
Awalnya, orang-orang yang lewat dan penonton bergegas untuk membantu. Seseorang menahan pria itu. Namun, meskipun Ali orang Lebanon, dia bukan berasal dari lingkungan ini; kita semua adalah orang asing.
“Mereka mata-mata!” pria yang menaiki skuter itu berteriak, dan kemudian beberapa orang lainnya berbalik untuk menanyai kami juga. “Apakah kamu mata-mata? Mengapa kamu mengambil foto itu?”
Seolah-olah penonton bisa berbalik melawan kami kapan saja, si agresor melepaskan diri dan menyerang sekali lagi untuk melawan, tapi untungnya kami bisa melarikan diri dan tidak menoleh ke belakang.
Di tengah kematian, kehancuran dan pengungsian yang kita saksikan di sini, kecurigaan dan ketidakpercayaan semakin meningkat dan, seiring dengan berlanjutnya perang, tampaknya bagi kita ketakutan ini akan semakin mengakar.