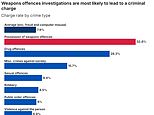TDataran Tinggi Laikipia di Kenya adalah suaka margasatwa dan tujuan safari populer, rumah bagi kelima hewan Afrika. Konflik lokal yang memanas antara komunitas penggembala asli dan petani kulit putih yang sudah berlangsung lama sejauh ini hanya mendapat sedikit perhatian dari komunitas internasional. Namun The Battle of Laikipia, yang dibuat oleh dua pembuat film veteran, sutradara dokumenter pemenang penghargaan asal Kenya Peter Murimi dan film pendek sutradara Yunani nominasi Oscar Daphne Matiaraki, berjalan di atas tali yang sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, krisis iklim telah meningkatkan kekerasan.
“Saat membuat film ini, saya terkejut dengan kenyataan bahwa orang-orang yang tinggal di lanskap yang sama hampir tidak mengenal satu sama lain dan tidak benar-benar memahami satu sama lain,” kata Machiaraki. “Kurangnya empati, rasa takut, dan terkadang penolakan untuk mengakui konteks sejarah adalah penyebab konflik ini semakin parah. Perubahan iklim memunculkan isu-isu yang telah disembunyikan selama beberapa dekade.”
Dalam pencarian karakter kuat, Murimi mengatakan warga Laikipia awalnya curiga dengan motif mereka. “Ketika seseorang mendengar Anda berbicara dengan musuh, itu akan menimbulkan banyak masalah,” katanya. Komunitas nomaden lokal telah menggunakan jalur penggembalaan kuno di Laikipia selama berabad-abad, namun ketika petani kulit putih mendapatkan akses ke lahan yang luas pada awal abad ke-20, kedua kelompok tersebut terlibat konflik.
Krisis iklim memaksa para penggembala, yang semakin membutuhkan rumput untuk ternak mereka, untuk berpindah ke lahan yang telah dimiliki oleh petani kulit putih selama beberapa generasi, sehingga meningkatkan risiko. Sebuah film dokumenter menunjukkan bagaimana pemilik tanah yang juga bergantung pada Laikipia untuk ternak mereka berjuang untuk meyakinkan para penggembala bahwa mereka juga warga Kenya dan bahwa Kenya adalah negara yang mereka kenal sepanjang hidup.
Machiaraki mengemukakan ide untuk film tersebut sekitar 20 tahun yang lalu saat tinggal di Kenya dan magang di UNEP. Dia bilang dia tahu sejak awal bahwa dia tidak bisa membuat film itu sendirian, itulah sebabnya dia meminta Murimi menjadi co-directornya. Adegan pertama yang diambilnya pada tahun 2017 menunjukkan karakter kuat dalam film tersebut, Maria Dodds, sedang minum teh bersama para tamu ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan di pertanian.
“Selalu menjadi tantangan untuk membuat film dari kedua sisi konflik, tetap netral, dan terus menumbuhkan kepercayaan dan keintiman sambil menjaga batasan etika,” kata Machiaraki. “Kami melihat orang-orang merasa takut, hancur, marah, mempertanyakan diri mereka sendiri, dan kemudian berdamai.”
Tokoh utama film ini adalah Simeon, seorang penggembala sapi Samburu, dan tiga pemilik tanah berkulit putih yang tinggal di dekatnya. Simeon yang berbicara bahasa Samburu sering digambarkan menghabiskan waktu bersama keluarganya di lingkungan yang sederhana. Dalam bahasa Samburu, “Nkishon” berarti kehidupan dan berasal dari kata “Ngishu” yang berarti sapi. “Sapi adalah kehidupan bagi kami,” kata Simeon dalam film tersebut. “Kami hidup dari susu, sup, darah, dan terkadang daging yang diberikan sapi kepada kami. Saat Samburu lahir, kami diberi seekor sapi. Dan saat kami mati, kami dikuburkan di dalam kulit sapi.”
Gaya hidup para penggembala berbeda dengan gaya hidup petani kulit putih, yang berbicara bahasa Inggris dan Swahili dan tinggal di rumah tangga yang lebih beruntung. Dalam salah satu adegan di awal film, seorang peternak memperingatkan seorang pemuda peternak kulit hitam untuk meninggalkan propertinya. Beberapa petani menggunakan pagar listrik untuk mencegah masuknya penggembala, namun banyak yang menerima bahwa lahan yang luas sulit untuk dikelola. “Pertanian ini sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang kita, kakek, dan kakek buyut kita. Rasanya seperti bagian dari keseluruhan teka-teki,” jelas Dodds. Film tersebut menggambarkan pemakaman Dodd yang meninggal karena kanker pada tahun 2021.
Warisan kompleks kolonialisme Inggris masih belum terselesaikan di Kenya, dan pemerintah enggan mencari solusi. Kemerdekaan Kenya pada tahun 1963 tidak banyak mengubah situasi tersebut, dan kepemilikan tanah tetap tidak berubah selama beberapa generasi. Berita televisi menayangkan aksi kekerasan baru-baru ini yang membuat para penggembala sering disebut sebagai “bandit”. “Menjadi semi-nomaden bukanlah suatu kejahatan,” kata Simeon di akhir film. Kekerasan terlihat jelas di kedua sisi. Seorang penggembala ditemukan tewas. Seorang petani menemukan bahwa kantornya telah dibobol.
Syuting dimulai pada tahun 2017 dan berlangsung selama lima tahun. Pada saat itu, terjadi kekeringan selama tiga tahun, sehingga pembuatan film ini menjadi tantangan logistik. “Tempatnya sangat terpencil, berpenduduk jarang dan terkadang harus berjalan jauh. Anda harus tidur di lantai, di atas kulit kambing atau kulit sapi. Sangat merendahkan hati menerima hal ini,” kata Murimi. Film sebelumnya adalah film dokumenter tahun 2020 “I Am Samuel,” tentang seorang pria gay dan pacarnya.
Murimi mengatakan rintangan terbesar dalam pembuatan film adalah “bias yang tidak disadari”. “Terkadang bias yang tidak disadari ini memengaruhi pekerjaan kami. Faktanya, kami harus benar-benar menantang satu sama lain saat membuat film ini bersama-sama, dan itu menjadikannya proses yang sangat bermanfaat. Ternyata memang demikian.”
“Kami juga belajar banyak tentang diri kami sendiri, karena terkadang orang mempunyai pandangan dunia seperti ini dan berpikir itulah satu-satunya cara dunia bekerja,” katanya. “Saya pikir keindahan dari proyek ini adalah ia menantang persepsi orang-orang, namun terkadang Anda harus melihat sisi lain untuk memahaminya. Dunia ini lebih dari yang kita kira. Dunia ini jauh lebih luas. Jadi menurut saya itulah tantangan terbesarnya. karena kami harus menghadapi kenyataan dan menerima bahwa terkadang kami salah.”