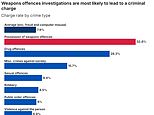Myanmar – Tersebar di perbukitan subur di wilayah Tanintharyi di selatan Myanmar, pejuang pemberontak yang ditempatkan di pos pemeriksaan memeriksa mobil dan truk yang melakukan perjalanan menuju kota terdekat yang masih berada di bawah kendali militer Myanmar – musuh mereka.
Meskipun hal ini merupakan pemandangan umum di wilayah tersebut, di mana perjuangan melawan militer yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda telah meningkat sejak kudeta tahun 2021, yang membedakan para pemberontak ini adalah keyakinan mereka.
Mereka adalah anggota “Perusahaan Muslim” yang kurang dikenal, yang bergabung dalam perjuangan demokrasi di Myanmar sebagai bagian dari kelompok bersenjata yang didominasi Kristen dan Budha – Persatuan Nasional Karen (KNU).
Secara resmi bernama Kompi ke-3 Brigade 4 di KNU, 130 tentara Kompi Muslim hanyalah sebagian kecil dari puluhan ribu orang yang berjuang untuk menggulingkan penguasa militer negara tersebut.
Dengan kisah mereka yang sebagian besar belum terungkap, Al Jazeera mengunjungi kantor pusat perusahaan tersebut, yang terletak di antara pegunungan yang diselimuti hutan di lokasi yang dirahasiakan di selatan Myanmar, untuk mengumpulkan benang merah yang hampir terlupakan dalam permadani rumit konflik Myanmar.
“Beberapa daerah fokus pada etnis yang memiliki negara sendiri,” jelas pemimpin Perusahaan Muslim Mohammed Eisher, 47, mengacu pada gerakan perlawanan bersenjata yang telah lama berperang melawan militer Myanmar.
Di Tanintharyi, kata Eisher, tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi wilayah tersebut dan, selain itu, represi militer berdampak pada semua kelompok.
“Selama militer masih berkuasa, umat Islam dan semua orang akan tertindas,” katanya.
Meskipun Eisher berharap penerimaan keberagaman dalam kelompok anti-militer akan membantu meredakan ketegangan budaya dan regional yang sebelumnya menyebabkan konflik di Myanmar, para pakar mengatakan bahwa dukungan dari Perusahaan Muslim menggarisbawahi sifat inklusif dari pemberontakan bersejarah yang terjadi. dan penggabungan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan ke dalam perjuangan.
Garis keturunan yang beragam
Umat Islam di Myanmar mempunyai garis keturunan yang beragam.
Mereka termasuk Rohingya di bagian barat negara itu, Muslim keturunan India dan Tiongkok, dan Kamein, yang nenek moyangnya diyakini adalah pemanah pangeran Mughal yang mencari perlindungan di kerajaan Arakan pada abad ke-17, dan kini menjadi bagian dari negara tersebut. dari Myanmar.
Di Tanintharyi, tempat berdirinya Perusahaan Muslim, sebagian Muslim adalah keturunan pedagang Arab, Persia, dan India, sementara yang lain adalah Melayu Burma, yang dikenal sebagai Pashu. Keberagaman etnis di kawasan ini juga mencakup antara lain Karen dan Mon, serta sub-etnis Bamar dari kota Dawei dan Myeik.
Sementara seragam mereka mempunyai lambang KNU, tentara Muslim dari Kompi ke-3 membawa lencana bintang dan bulan sabit di tas mereka, melambangkan garis keturunan mereka dari Tentara Pembebasan Muslim Seluruh Burma (ABMLA) – negara ini disebut “Burma” sebelum direbut kembali. -bernama “Myanmar”.

Di kamp utama mereka, penutup kepala dan thobe – jubah tradisional berlengan panjang sepanjang mata kaki yang sering dikenakan oleh pria dan wanita di negara-negara Muslim – merupakan pakaian umum. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran terdengar dari sebuah masjid, sementara sajadah diletakkan di pos-pos pemberontak yang terpencil. Sepanjang bulan suci Ramadhan, para pejuang perusahaan menjalankan puasa dan melaksanakan salat sehari-hari.
Pemerintahan yang dipimpin militer di Myanmar, bersama dengan para biksu nasionalis garis keras, telah menggambarkan umat Islam sebagai ancaman besar terhadap budaya Budha di Burma. Hal ini mengakibatkan komunitas Muslim, yang sudah memiliki akar lebih dari satu milenium di Myanmar, menghadapi kambing hitam, penindasan agama, dan penolakan kewarganegaraan.
“Berbahaya untuk melakukan generalisasi, namun umat Islam di Myanmar sangat rentan dan mengalami kekerasan yang signifikan,” kata pakar Myanmar Ashley South.
“Namun, di wilayah Karen, sering kali kita menemukan komunitas yang hidup dengan damai – dan penting bagi pengungsi Muslim untuk pindah sementara ke wilayah yang dikuasai KNU, terkadang lebih memilih kelompok lain,” kata South.
Dia menambahkan bahwa masuknya kelompok-kelompok yang sebelumnya diasingkan oleh politik Myanmar yang terpecah belah adalah ciri khas revolusi saat ini, yang telah memperoleh keuntungan besar dalam melawan militer sejak mereka merebut kekuasaan pada tahun 2021.
Sejarah perlawanan umat Islam
Kaum Muslim yang melawan militer setelah penggulingan pemerintahan terpilih Myanmar tiga tahun lalu dan kemudian berhasil masuk ke Kompi ke-3, bukanlah kelompok pertama yang bangkit melawan penindasan.
Di antara mereka yang melarikan diri dari kerusuhan anti-Muslim pada bulan Agustus 1983 di tempat yang dulu bernama Moulmein – sekarang disebut Mawlamyine – di wilayah hilir Burma, sekelompok kecil pengungsi membentuk Front Pembebasan Muslim Kawthoolei (KMLF) di wilayah yang dikuasai KNU.
KNU melatih sekitar 200 pejuang KMLF, namun perselisihan antara pemimpin Sunni dan Syiah akhirnya memecah belah kelompok tersebut.
Pada tahun 1985, beberapa pejuang KMLF pindah ke selatan ke Tanintharyi, mendirikan ABMLA. Setelah beberapa dekade mengalami bentrokan sporadis dengan militer, mereka secara resmi menjadi Kompi ke-3, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “Kompi Muslim”. Hal itu terjadi sekitar tahun 2015, setelah gencatan senjata KNU dengan militer berakhir, menurut seorang administrator yang telah bergabung dengan kelompok tersebut sejak tahun 1987.
Dengan kekejaman militer yang telah menghancurkan banyak keluarga di seluruh Myanmar sejak pengambilalihan baru-baru ini, tentara Myanmar kini menjadi kutukan tidak hanya bagi umat Islam dan etnis minoritas tetapi juga bagi sebagian besar penduduknya, kata administrator tersebut.
“Kudeta (2021) membuka jalan menuju kebebasan bagi semua orang,” tambahnya, berbicara kepada Al Jazeera sambil duduk di tempat tidur gantung di atas sepasang sepatu bot militer yang diambil dari pangkalan pemerintah yang direbut.
Sekitar 20 wanita bertugas di Kompi ke-3, termasuk Thandar* yang berusia 28 tahun, seorang petugas medis yang bergabung pada Oktober 2021. Setelah menyelesaikan pelatihan tempur di bawah KNU, Thandar menceritakan bagaimana dia mendengar tentang pasukan Muslim dan memutuskan untuk mendaftar.

“Saya akan bekerja di sini sampai revolusi selesai,” katanya sambil tersenyum kepada komandan mereka, Eisher. “Dia seperti ayah baruku sekarang,” katanya.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bergabung dengan kelompok pejuang yang berpikiran sama “mempermudah pola makan halal”, katanya.
“Ditambah lagi, saya bersama sesama Muslim,” tambahnya. “Di sini bagus. Itu sebabnya saya tinggal di sini begitu lama.”
‘Kebebasan bagi seluruh rakyat Burma’
Sekitar 20 calon Muslim yang melarikan diri dari undang-undang wajib militer rezim militer, yang diberlakukan pada tahun 2010 tetapi baru diaktifkan tahun ini di Myanmar, baru-baru ini mendaftar wajib militer, kata Eisher.
Selama kunjungan Al Jazeera ke perusahaan tersebut, tentara di kamp utamanya sebagian besar adalah pria yang sudah menikah, dan menggunakan cuti mereka untuk mengunjungi keluarga di dekatnya. Sebuah barak terpisah menampung orang-orang sakit, biasanya para pria muda yang pernah terkena penyakit malaria sebelumnya.
Masjid di dekat kamp adalah sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari balok angin dengan atap seng, dan pipa plastik di dinding luar untuk wudhu sebelum salat.
Eisher menceritakan bagaimana imannya diuji pada tahun 2012 saat terjadi bentrokan dengan militer, ketika dia ditembak di leher dan lengan kanan atas. Terpisah dari unitnya, dia berjalan sendirian selama dua hari sebelum menemukan rekan-rekannya, yang membawanya selama lima hari melewati hutan lebat.
“Bau nanah dari luka di leher saya membuat saya muntah-muntah,” kenangnya sambil menyentuh bekas luka bekas peluru yang keluar dan mengingat betapa kerasnya ia berdoa.
“Saya berdoa agar dosa-dosa saya diampuni, jika saya melakukan kesalahan apa pun, dan jika tidak, agar diberikan kekuatan untuk terus berjuang,” katanya.
Di sebuah pos terdepan jauh di dalam hutan wilayah Kompi ke-3, Mohammed Yusuf, 47 tahun, memimpin satu unit pejuang. Seperti Eisher, Yusuf juga menderita karena hal tersebut. Dua puluh tahun yang lalu, saat membersihkan ranjau darat, sebuah ranjau meledak dan membutakannya.
“Saya ingin kebebasan bagi seluruh rakyat Burma,” katanya. “Revolusi akan berhasil, namun perlu lebih banyak persatuan. Setiap orang harus tetap setia pada tujuannya.”

Kompi Ketiga juga memiliki keragaman internal, termasuk beberapa anggota Budha dan Kristen di kamp utama.
Salah satu umat Buddha, seorang petani Bamar berusia 46 tahun yang berubah menjadi revolusioner dengan senyum tenang, menanam terong dan kacang panjang untuk dimakan para pejuang.
Setelah menjadi sukarelawan bersama dua kelompok perlawanan lainnya, dia menceritakan bagaimana dia menyadari bahwa tempatnya adalah di “Perusahaan Muslim”.
“Tidak ada diskriminasi di sini,” katanya.
“Kita semua sama – manusia.”
*Thandar adalah nama samaran karena narasumber meminta agar namanya tidak digunakan dalam artikel ini.