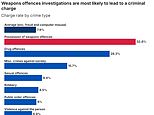Dua ratus tahun yang lalu, perkebunan kopi di São Jose do Pinheiro, 120 km (75 mil) dari Rio de Janeiro, termasuk yang termewah di Brasil.
Bahkan bagi negara yang menerima jumlah terbesar orang Afrika yang diculik dalam perdagangan budak Atlantik, kekayaan ini tergolong unik.
Sekitar 500 orang, jumlah tenaga kerja yang luar biasa besar bahkan menurut standar Brasil, diperbudak oleh José de Souza Braves, salah satu orang terkaya di Brasil, yang memiliki delapan perkebunan lain di wilayah tersebut.
Piñeiro adalah bentengnya, dengan banyak bangunan termasuk istana dengan 20 kamar yang dipenuhi karya seni dan rumah sakit dengan 48 tempat tidur untuk pekerja yang diperbudak, sarana untuk mencegah hilangnya produktivitas karena penyakit atau cedera serius.
Saat ini, Pinheirar, sebuah kota berpenduduk 24.000 orang yang dinamai berdasarkan nama pertanian tersebut, berdiri di tempat pertanian tersebut dulu berdiri.
Sisa-sisa istana yang dipenuhi grafiti dan dikelilingi vegetasi lebat, kini menjadi ruang publik bernama Taman Reruntuhan.
Dan situs-situs yang pernah menjadi rumah bagi kerajaan pemilik budak diklaim oleh keturunan mereka yang pernah dipaksa bekerja di sana.
Mereka baru-baru ini mendapatkan dana dari pemerintah Brasil untuk mengubah Ruins Park menjadi museum dan sekolah untuk jongo, sebuah tradisi Afro-Brasil yang menggabungkan musik, tari, spiritualitas, dan bercerita.
“Kami berjuang keras untuk mendapatkan kembali tanah yang dulunya milik pedagang budak, dan kini menjadi milik kami,” katanya. John Gayla Cintia Helena da Silva, 34, yang nenek moyangnya diperbudak di Piñeiro.
“Saya sudah mengikuti jongo sejak kecil. Nenek dan ibu saya ikut, paman saya adalah seorang master, dan sekarang saya membawa suami dan anak saya,” kata Derrick Abayomi, 3 tahun, sambil menunjuk.
Keluarga Da Silva adalah bagian dari kelompok Yongo de Pinheirar, yang mengambil alih ruang tersebut pada tahun 2016 melalui perjanjian dengan Balai Kota dan saat ini menjalankan proyek museum.
Pada akhir pekan baru-baru ini, grup tersebut mengadakan festival di Pinheiro yang menampilkan 18 grup jongo berbeda. Ini adalah area datar dan luas yang sama dimana biji kopi disebar dan dikeringkan di bawah sinar matahari pada tahun 1800an.
Proses persidangan dibuka oleh María de Fátima da Silveira Santos, 68 tahun, yang cincin, gelang, gelang dan kalungnya membuktikan otoritasnya sebagai pemimpin Jongo de Piñerar.
Pemimpin yang dikenal sebagai Mestre Fatinha bernyanyi, “Saya datang untuk memberkati tanah yang saya injak.”
dari jon gueiros Membentuk lingkaran, dua orang bermain drum dan Mestre Fatinha menyanyikan sebuah lagu. titiklalu semua orang mengikuti.
Liriknya berkisar dari tema yang tampaknya biasa-biasa saja (“Jangan Sebut Nama Saya”) hingga tema yang lebih politis yang secara langsung merujuk pada perbudakan. ”
Pertunjukan yang berlangsung berjam-jam dan terkadang berlangsung sepanjang malam ini biasanya hanya melibatkan dua orang dalam satu waktu, sering kali seorang pria dan seorang wanita menari di atas ring. Tidak ada koreografi. Semua orang menari sesuka mereka. Setelah beberapa gerakan, mereka digantikan satu per satu.
Kelihatannya seperti sebuah tarian, tapi selalu ada yang lebih dari itu, kata Mestre Fatinha. “Jongo adalah sarana komunikasi bagi orang kulit hitam. Mereka berpolitik, saling pacaran, dan beribadah kepada Tuhan. Orisha (Dewa agama Afro-Brasil Candomblé). “Itu semua terjadi di lingkaran Django,” katanya.
Masalah-masalah serius dapat didiskusikan dalam lagu, dan bahkan pemberontakan dapat diorganisir dengan pesan-pesan berkode tepat di depan para budak.
Menurut sejarawan dan etnomusikolog Rafael Galante, kata “jongo” berasal dari rumpun bahasa Bantu, yang merupakan milik sebagian besar orang Afrika yang dibawa ke Brasil pada abad ke-19.
Meskipun tidak ada konsensus mengenai arti pastinya, salah satu penafsirannya adalah bahwa kata tersebut mengacu pada ruang komunal untuk mediasi politik, sosial, dan agama.
Meskipun menggabungkan unsur-unsur yang ditemukan dalam beberapa budaya Afrika Tengah, jongo adalah fenomena unik di Brasil, hasil dari “pengalaman diaspora,” kata Galante, sambil menambahkan, “Ini adalah kisah perbudakan melawan perbudakan.” perspektif mereka yang menderita.”
Mestre Fatinha setuju. “Jongo kami masih sama seperti di masa perkebunan, diwariskan dari generasi ke generasi.”
Saat ini, ia juga mengambil peran baru, katanya. “Ini adalah panji perjuangan kami sebagai orang kulit hitam…Sekarang kami menggunakannya di tempat-tempat seperti sekolah dan universitas untuk membicarakan tentang warisan kami.”
Jongo dipraktikkan di setidaknya 14 komunitas tradisional di Brasil tenggara. Banyak di antaranya merupakan sisa-sisa dari hal tersebut Quilombosjuga berasal dari kata Bantu, merujuk pada komunitas yang didirikan oleh para budak yang melarikan diri selama 350 tahun perbudakan di Brasil.
Jongo bukanlah agama, tapi melibatkan spiritualitas. Dalam beberapa lagu, Orisha dan tokoh Katolik, termasuk St. Benediktus dari Afrika.
“Kami selalu mengenang nenek moyang kami, karena tanpa mereka kami tidak akan ada di sini… Kami menari untuk mengenang mereka,” kata Mestre Fatinha. Sebuah proyek untuk mengubah reruntuhan rumah besar Piñeiro menjadi monumen bagi orang kulit hitam.
Selain museum dan Sekolah Jongo, rencananya juga mencakup restoran, pusat pengunjung, perpustakaan, dan pelestarian reruntuhan, yang telah memburuk secara signifikan karena diabaikan selama bertahun-tahun.
Anggaran proyek keseluruhan adalah 5 juta reais (£705,844 atau $890,513), namun sejauh ini pemerintah Brasil telah menyetujui 300,000 reais (42,351 pound) untuk pengembangan proyek eksekutif pound, atau $54,817). Konstruksi diperkirakan baru akan dimulai tahun depan.
“Rumah besar Piñeiro pernah menjadi salah satu simbol terbesar kekayaan perbudakan di Brasil,” kata Galante.
“Dan orang-orang yang selamat dari semua kekerasan itu kini mengklaim ruang itu untuk mengubahnya menjadi pusat kenangan. Tidak ada yang ingat siapa budak itu, tapi di sini Anda menulis tentang Jongo.”