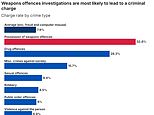Pada tanggal 5 Oktober, Israel melancarkan operasi militer darat, menuntut evakuasi warga Palestina yang tinggal di Beit Hanoon, Beit Lahiya, kamp pengungsi Jabalia, dan kota Jabalia. Hal ini kemudian menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, sehingga menyebabkan lembaga-lembaga bantuan memperingatkan bahaya kelaparan yang akan segera terjadi.
Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan kekuatan perlawanan Palestina yang berkumpul kembali di utara. Namun, para pengamat mencatat bahwa serangan baru ini mungkin merupakan tahap pertama dari apa yang oleh media Israel disebut sebagai “Rencana Umum” pembersihan etnis di Gaza utara sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga Palestina.
Rencana tersebut diajukan oleh purnawirawan Jenderal Giora Eiland dan menyerukan pengusiran warga Palestina dari wilayah tersebut dan pemaksaan kelaparan serta penargetan terhadap siapa pun yang tetap tinggal – untuk dianggap sebagai “target militer yang sah”. Pada sesi Komite Pertahanan Luar Negeri Knesset pada bulan September, Eiland dilaporkan dikatakan: “Yang penting bagi (pemimpin Hamas Yahya) Sinwar adalah tanah dan martabat, dan dengan manuver ini, Anda merampas tanah dan martabat.”
Seminggu kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi tahu anggota komite yang sama bahwa dia juga ikut serta mempertimbangkan melaksanakan usulan tersebut. Kemungkinan besar dia berharap rencana tersebut dapat memberinya kesempatan untuk mendeklarasikan “kemenangan” untuk menyelamatkan mukanya di hadapan publik Israel, mengingat setahun setelah perang, pemerintahannya masih belum mencapai tujuannya untuk “menghancurkan Hamas”.
Namun, Israel diragukan memiliki kapasitas militer dan ruang politik untuk melaksanakan proposal Eiland secara penuh.
Ada beberapa alasan mengapa Israel berusaha memutus dan menguasai bagian utara Jalur Gaza. Pertama, mereka ingin memisahkan Kota Gaza, pusat administrasi Jalur Gaza dan pusat kekuasaan politik, dari wilayah lainnya, sehingga menghancurkan infrastruktur fisik pemerintahan Palestina. Hal ini mempunyai arti penting secara politis.
Kedua, Kota Gaza adalah pusat layanan sosial utama, tempat rumah sakit utama Gaza, Kompleks Medis al-Shifa, dan sebagian besar universitasnya berada. Banyak organisasi nirlaba, dunia usaha, dan sebagian besar kelas menengah Gaza bermarkas di sana. Banyak keluarga terkemuka yang secara historis terkait dengan pemerintahan wilayah Gaza berasal dari kota tersebut. Hilangnya Kota Gaza akan memberikan dampak sosial yang luar biasa terhadap penduduk Palestina.
Ketiga, bagian utara Jalur Gaza juga penting bagi Israel dari sudut pandang keamanan. Ini adalah rumah bagi kamp pengungsi Jabalia, yang terbesar di Palestina, tempat Intifada Palestina pertama dimulai dan tempat beberapa kampanye militer besar Israel digagalkan.
Gaza Utara juga dekat dengan lokasi-lokasi penting Israel, seperti pelabuhan Ashkelon, yang terletak hanya 10 km (6 mil) dari perbatasan Gaza. Sebagian besar penduduk Israel bagian selatan tinggal di wilayah Ashkelon-Ashdod. Kontrol atas pantai utara Gaza juga dapat menjamin keamanan yang lebih besar bagi wilayah selatan Israel dan infrastruktur pengeboran gasnya dan mungkin membantu pengambilan ilegal ladang gas Laut Gaza.
Dengan mengingat semua hal ini, tentara Israel memulai persiapan untuk memperluas kendali atas Gaza utara jauh sebelum “Rencana Umum” diumumkan sebagai kebijakan resmi. Pada bulan November tahun lalu, mereka mulai mengerjakan apa yang kemudian dikenal sebagai Koridor Netzarim, sebidang tanah yang membentang dari perbatasan resmi Israel hingga Laut Mediterania yang memisahkan Gaza utara dari bagian tengah dan selatannya.
Koridor tersebut, selebar 4 km (2,5 mil), memberi tentara Israel keuntungan logistik dan taktis yang signifikan, memungkinkan mereka untuk memasok pasukannya yang ditempatkan di Kota Gaza dan Jalur Gaza tengah dan untuk mengendalikan aliran bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza utara.
Ditunjuk sebagai zona militer tertutup, zona ini mencegah warga Palestina bergerak kembali ke utara dari selatan, karena siapa pun yang mencoba masuk berisiko ditembak. Pasukan Israel ditempatkan di beberapa titik di sepanjang koridor, menggunakannya sebagai basis utama untuk mengumpulkan pasukan dan melancarkan operasi militer.
Sepanjang tahun lalu yang dilanda perang tanpa henti, Israel telah berulang kali mengeluarkan perintah evakuasi ke wilayah utara dan berusaha mengusir penduduk yang tersisa dengan mengurangi akses bantuan kemanusiaan, melakukan pengeboman, menyerbu dan menghancurkan pusat kesehatan dan rumah sakit serta menargetkan infrastruktur penting lainnya seperti air sumur dan listrik. generator. Mereka juga secara sistematis menargetkan bangunan tempat tinggal dan sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan untuk menghilangkan tempat berlindung dan menyebarkan ketakutan. Akibatnya, diperkirakan 400.000 orang masih tinggal di wilayah utara dari total populasi sebelum perang 1,1 juta.
“Rencana Umum” mencakup peningkatan semua kegiatan ini untuk sepenuhnya memaksa warga Palestina keluar dari Gaza utara. Setelah wilayah tersebut dibersihkan dari penduduknya, tentara Israel akan menyatakannya sebagai zona militer tertutup, sehingga warga Palestina tidak dapat mengakses rumah dan tanah mereka.
Jika Israel juga tetap menguasai Rafah di selatan, maka hal ini akan secara efektif membatasi sebagian besar penduduk Gaza di wilayah yang lebih kecil dan padat penduduk di tengah atau di sepanjang pantai, sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang mengerikan. Strategi ini dapat menekan sebagian penduduk untuk meninggalkan Jalur Gaza seiring berjalannya waktu. Mengadvokasi tindakan tersebut, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah berulang kali menyerukan kebijakan yang akan memaksa warga Palestina melakukan “emigrasi sukarela” dengan menciptakan kondisi kehidupan yang tidak tertahankan.
“Rencana Umum” mungkin berhasil jika Israel melaksanakannya tanpa kendala waktu dan sumber daya. Namun, kecil kemungkinannya militer Israel dapat mempertahankan operasi di Gaza tanpa batas waktu, terutama dengan perang yang sedang berlangsung dengan Lebanon yang menuntut pengerahan pasukan dalam jumlah besar dan fokus strategis serta potensi eskalasi dengan Iran. Semangat ketabahan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang masih tinggal di Gaza utara juga menjadi tantangan bagi efektivitas rencana ini.
Lebih lanjut, patut dipertanyakan berapa lama pasukan Israel dapat mempertahankan posisi mereka di Gaza utara tanpa menderita banyak korban akibat perlawanan Palestina yang terus beroperasi di sana. Hal ini hanya mungkin terjadi jika Israel mencapai kemenangan yang menentukan, yang mengharuskan penghancuran kelompok perlawanan. Namun perkembangan selama setahun terakhir menunjukkan bahwa hal ini bukanlah hasil yang realistis.
Tekanan eksternal juga merupakan faktor penting. Negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, secara konsisten menentang perpindahan besar-besaran penduduk Palestina keluar dari Jalur Gaza. Pembersihan etnis di wilayah utara bisa menjadi langkah pertama untuk mengusir warga Palestina keluar dari perbatasan Jalur Gaza. Tindakan seperti ini akan mengganggu stabilitas negara-negara tersebut dan berisiko memicu fase baru konflik – sebuah perkembangan yang dikhawatirkan tidak hanya terjadi di Kairo dan Amman namun juga di seluruh kawasan. Hal ini mungkin memaksa negara-negara Arab untuk bertindak lebih dari sekadar kecaman verbal.
Tekanan terhadap Israel juga meningkat di Eropa. Meskipun negara-negara Uni Eropa telah gagal untuk mengambil sikap terpadu terhadap perang Israel di Gaza, semakin banyak negara yang secara terbuka menyuarakan dukungan untuk tindakan tegas. Prancis menyerukan embargo senjata, sementara Spanyol mendesak pembubaran perjanjian perdagangan bebas dengan Israel.
Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat, sekutu terbesar Israel, juga menerapkan retorika yang lebih keras terhadap Israel, dengan memperingatkan pemerintah Israel bahwa mereka dapat menghentikan pasokan senjata jika tidak memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza. Meskipun banyak pengamat menyebut peringatan ini sinis, mengingat dukungan tak tergoyahkan Presiden Joe Biden terhadap Tel Aviv selama setahun terakhir, pemerintahannya akan segera berakhir.
Dengan kata lain, Israel mempunyai ruang gerak yang dijamin oleh Gedung Putih hingga pemilu AS pada awal November atau mungkin hingga pemerintahan baru mengambil alih pada bulan Januari. Siapa pun presiden AS berikutnya, mereka akan terpaksa mengatasi tindakan Israel di Gaza, mengingat tindakan tersebut adalah sumber ketidakstabilan di seluruh kawasan dan perang regional yang meluas. Konflik terbuka dan berkepanjangan di Timur Tengah bukanlah kepentingan strategis AS, karena dapat membahayakan tujuan regionalnya yang lebih luas.
Sampai tekanan internasional meningkat, Amerika Serikat mengubah kebijakannya atau ada peristiwa politik internal yang mempengaruhi opini publik Israel, pemerintah Israel kemungkinan akan terus menjalankan “Rencana Umum” tanpa secara resmi mengakui niatnya. Pengusiran warga Palestina dari Gaza utara akan ditampilkan sebagai pencapaian militer di mata masyarakat Israel, sementara pertanyaan mengenai keberlanjutannya dalam jangka panjang kemungkinan besar tidak akan terjawab.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.