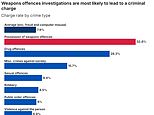Bagi Amani Ahmed, kehidupan barunya di Edinburgh bersama keluarganya yang sedang belajar gelar PhD di salah satu universitas ternama di Inggris adalah hal yang pahit dan manis. Dia memeriksa teleponnya setiap hari, takut dia akan menerima pesan bahwa ibu, saudara laki-laki dan perempuannya telah ditemukan di bawah reruntuhan di Gaza.
“Secara fisik saya di sini, tapi secara mental saya merasa berada di Gaza,” katanya.
“Saya kehilangan ayah saya, tapi saya bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Kami meninggalkan Gaza, tapi kami terjebak dalam pikiran kami sendiri. Itu adalah tempat di mana kami tinggal. Ya, keluarga besar, saudara, teman… semuanya di sana. Kami memeriksa media sosial dan takut mendengar seseorang dibunuh.”
Ahmed adalah dosen dan kepala departemen hubungan internasional di Universitas Islam Gaza, yang kini berada di bawah reruntuhan akibat pemboman berulang kali.
Meski begitu, dia menganggap dirinya beruntung. Dia akan memulai gelar PhD dengan beasiswa di Universitas Edinburgh pada tahun 2022, dalam perjalanan antara Gaza dan Skotlandia. Dia kembali ke Edinburgh pada awal Oktober 2023 setelah liburan musim panas, tetapi kemudian invasi Israel dimulai dengan sungguh-sungguh.
Rencananya untuk mewawancarai pengusaha perempuan di Jalur Gaza untuk penelitian gagal karena perang, namun yang paling mengganggunya adalah dia meninggalkan keluarganya, termasuk suaminya, dua putri remajanya, dan seorang putra berusia 8 tahun harus dilakukan.
“Saya merasa cemas. Saya pikir saya harus kembali ke Gaza untuk bersama anak-anak saya, namun perbatasan ditutup,” katanya. “Tiga hari setelah perang dimulai, terjadi pemboman besar-besaran dan serangan udara di sekitar apartemen kami di Gaza. Anak-anak dan suami saya kehilangan nyawa ketika pemboman dramatis tersebut menyebabkan jendela-jendela runtuh dan kaca berserakan di mana-mana memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke rumah teman, tapi saat itu tidak aman untuk bepergian.”
Ahmed adalah salah satu dari dua peneliti Palestina pertama yang menerima dukungan dari Dewan Akademisi dalam Krisis (Cara), yang memberikan bantuan kepada akademisi yang berisiko mengalami penganiayaan, kekerasan, dan konflik.
Badan amal tersebut mengatakan bahwa warga Palestina merupakan akademisi dengan jumlah terbesar yang membutuhkan bantuan darurat, sehingga mendorong permintaan ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 1930an.
Sejak Oktober 2023, badan amal tersebut telah menerima 120 lamaran dari warga Palestina dan sedang mengerjakan 13 di antaranya. Salah satu akademisi, yang menjabat sebagai dekan di Universitas Gaza, telah ditempatkan sebagai peneliti tamu di Universitas Cambridge.
Kondisi pendidikan di Palestina saat ini sulit. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas, 120 akademisi terbunuh Mulai 7 Oktober 2023, laporan PBB Ditemukan Diperkirakan 80% sekolah dan universitas akan hancur.
Kara membantu mengatur keluarga Pak Ahmed untuk mendapatkan visa tanggungan pelajar, dengan biaya selangit yang diperkirakan oleh Pak Ahmed lebih dari £10.000 ditambah biaya hidup.
Setelah berbulan-bulan Ahmed tidak bisa tidur selama berbulan-bulan, di mana dia memeriksa teleponnya setiap jam untuk mengetahui kabar terbaru, keluarga tersebut akhirnya berkumpul kembali tepat pada saat Ramadhan di bulan April. Dia ingat dengan jelas video yang dikirim suaminya kepadanya tentang putranya yang menangis panik dan berkata, “Saya tidak ingin mati.”
Saat itu, dia resah dengan apa yang dilihatnya di media sosial. “Saya melihat keluarga-keluarga terperangkap di bawah reruntuhan, anak-anak terbunuh, orang-orang masih hidup namun anggota tubuhnya hilang. Suatu hari saya terbangun dan mendapat pesan yang mengatakan bahwa rumah saya telah dibom.
Orang tuanya, saudara perempuan, saudara laki-lakinya, dan keluarganya sendiri tinggal di rumah yang sama. “Itu bukan masa yang mudah. Saya berdoa, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa tidak berdaya. Ada kalanya saya tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan mereka karena listrik padam.”
Kakak perempuan, saudara laki-laki dan ibunya saat ini tinggal di tenda-tenda di kamp al-Nuseirat, yang sering mendapat perintah pengeboman dan evakuasi.
Meskipun keluarganya menganggap diri mereka beruntung, mereka menghadapi tantangan untuk berintegrasi ke dalam komunitas baru mereka. Putri tertua Ahmed, 16 tahun, berada pada “tahap kritis dalam hidupnya”, mulai dari seorang siswa berprestasi yang ingin meraih gelar kedokteran hingga berjuang secara akademis dan tidak tahu bagaimana dia akan membiayai studinya.
Namun ada hikmahnya, Ahmed memfokuskan penelitiannya pada pengusaha perempuan di Tepi Barat karena pembatasan perjalanan yang diberlakukan Israel. Saya belum pernah mengunjungi Tepi Barat. Dia terdorong oleh “rasa solidaritas dan dukungan” yang dia rasakan dari para wirausahawan ini dan kesempatan untuk berkontribusi pada penelitian yang dapat membantu membangun kembali perekonomian negara.
Dia juga terus bekerja di universitas, membantu para pengungsi mendapatkan peluang pertukaran di negara lain. “Saya masih terlibat dan berharap dapat mendukung lebih lanjut setelah saya menyelesaikan PhD saya,” ujarnya.