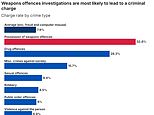Serangan jihadis di ibu kota Mali pada hari Selasa dilaporkan menyebabkan banyak orang tewas, sekali lagi menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan junta untuk melawan pemberontakan yang telah berlangsung selama 12 tahun.
Ekstremis Islam menyerang banyak lokasi di Bamako, termasuk sekolah pelatihan elit polisi. Kekerasan tersebut diklaim oleh afiliasi al-Qaeda Jamaah Nusrat ul-Islam al-Muslim (JNIM), dan bandara kota ditutup pada hari itu.
Pihak berwenang mengatakan mereka telah memadamkan kerusuhan dan mengakui di televisi pemerintah bahwa ada korban jiwa, namun tidak memberikan angka pastinya.
Namun, sumber keamanan mengatakan kepada Agence France-Presse pada hari Kamis bahwa 77 orang tewas dan 255 luka-luka. AFP juga melaporkan bahwa dokumen resmi rahasia yang bersertifikat menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100 orang, dan menyebutkan 81 korban. Surat kabar Belgia Le Soir melaporkan bahwa pemakaman sekitar 50 mahasiswa polisi militer diadakan pada hari Kamis.
Seorang pejabat keamanan yang berada di dalam kamp pelatihan pada saat serangan terjadi mengatakan kepada Associated Press tanpa menyebut nama bahwa setidaknya 15 tersangka telah ditangkap.
Sebuah pesawat yang digunakan oleh Program Pangan Dunia (WFP) juga rusak di bandara. Juru bicara WFP Jauncede Majangal mengatakan pesawat itu digunakan untuk “mengangkut pekerja bantuan dan memberikan bantuan kemanusiaan darurat di daerah terpencil di Mali.”
“Ini bukan satu-satunya pesawat yang kami gunakan di Mali, namun mengingat banyaknya tujuan yang kami miliki, hal ini mengurangi kapasitas tanggap kemanusiaan yang kami berikan kepada warga sipil,” tambahnya.
Maskapai penerbangan Afrika Selatan National Airways Corporation mengumumkan bahwa sebuah pesawat penumpang yang disewa dari mereka diserang di darat di Bamako. Majangal mengatakan seluruh awak kapal dan staf tidak terluka.
Pada tahun 2012, pemberontakan Tuareg berubah menjadi pemberontakan yang tidak mampu dipadamkan oleh Mali. Aktivitas jihadis telah menyebar ke seluruh wilayah Sahel, sehingga meningkatkan kekhawatiran di kalangan pemimpin di pesisir Afrika Barat bahwa aktivitas militan di hilir tidak dapat dihindari. Lebih dari 1.600 warga sipil terbunuh dalam sembilan bulan pertama tahun 2023, meningkat 17% dari tahun sebelumnya, menurut statistik dari organisasi nirlaba Lokasi Konflik Bersenjata dan Data Peristiwa (Acled).
Serangan itu terjadi ketika Asosiasi Negara-Negara Sahel (AES), yang dibentuk oleh Mali, Niger dan Burkina Faso, mengumumkan rencana untuk menerbitkan paspor baru di luar Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (Ecowas). Langkah ini, jika diterapkan, akan memperkuat independensi AES dari blok-blok regional yang diklaim dimanipulasi oleh kepentingan Barat.
Perpecahan di Ecowa antara lain disebabkan oleh pendudukan militer di Mali, dimana pimpinan sipil dianggap tidak mampu memadamkan pemberontakan meski hadirnya pasukan Perancis. Faktor lain yang menyebabkan ketegangan adalah penggunaan tentara bayaran Rusia oleh Mali untuk membantu mengatasi pemberontakan di wilayahnya.
Tentara bayaran Grup Wagner Rusia baru-baru ini menderita serangkaian kerugian di wilayah tersebut. Insiden terbaru, dan mungkin paling kejam, terjadi pada bulan Juli ketika pemberontak menyergap konvoi pasukan Mali dan Korps Afrika milik Moskow di Tinsawatene, dekat perbatasan dengan Aljazair.
Militer Mali mengatakan lebih dari 20 pemberontak tewas dalam bentrokan tersebut, sementara JNIM mengklaim 50 warga Rusia dan 10 tentara Mali tewas, meski angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.
Insiden tersebut menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Ukraina, dan Kiev mengklaim pihaknya telah berbagi informasi intelijen dengan pemberontak.