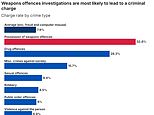GKementerian Kesehatan Aza telah mengidentifikasi 34.344 warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di wilayah tersebut, dengan nama, usia, jenis kelamin, dan nomor ID yang mencakup lebih dari 80% warga Palestina yang tewas dalam perang tersebut sejauh ini.
The Guardian menggunakan daftar ini untuk menemukan keluarga korban tertua, korban berusia 101 tahun, dan salah satu korban termuda, bayi baru lahir yang hidup singkatnya hanya berlangsung dua jam. Kisah mereka adalah sebagai berikut.
Ahmed Al Tahrawi
Pekerjaan pertama Tahrawi adalah sebagai juru masak di kamp tentara Inggris dekat desanya, ketika tanah airnya masih menjadi bagian dari Mandat Palestina dan memerintah dari London.
Ia lahir di al-Masmiyyah pada tahun 1922, namun kini reruntuhan tersebut menjadi salah satu dari sedikit reruntuhan yang ada dalam ingatan, hanya ada sebagai nama persimpangan jalan Israel sekitar 30 menit berkendara dari perbatasan utara Gaza.
Penduduk dievakuasi selama Nakba tahun 1948, ketika sekitar 700.000 warga Palestina diusir dari tanah air mereka setelah pembentukan negara Israel.
Tahrawi berusia 26 tahun pada tahun itu dan ayah dari dua anak laki-laki. Menurut cucunya Abd al-Rahman al-Tahrawi, keluarga tersebut meninggalkan kehidupan lama mereka dengan berjalan kaki, hanya membawa kunci rumah desa mereka, yang tidak akan pernah mereka lihat lagi.
Anak-anak lelaki tersebut tidak dapat bertahan hidup di pengasingan, sehingga di kamp pengungsi Breiji di Gaza, Ahmed al-Tahrawi dan istrinya mulai membangun kembali keluarga, rumah, dan kehidupan mereka dari awal. Kunci keluarga Masmiyya selalu digantung di dinding, di mana pun mereka tinggal, mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah hilang.
Tahrawi bekerja sebagai penjahit, kemudian mengelola toko kecil dan membesarkan keluarga besar yang penuh kasih sayang selama beberapa generasi. Dia hidup cukup lama untuk bertemu dengan cicitnya dan tetap sehat secara mental dan fisik sampai akhir.
Dalam video keluarga yang diambil beberapa bulan sebelum perang, ketika dia sudah berusia 100 tahun, dia mencoba belajar bagaimana mengatakan “Aku cinta kamu” dalam bahasa Inggris kepada istrinya. Saat dia menirukan kata-kata asing itu sambil tersenyum, ruangan itu dipenuhi tawa. Kunci rumah tua tergantung di dinding di belakangnya.
“Dia akan segera meninggalkan kita, tapi dia tidak mengambil jalan yang normal,” kata cucunya.
Rumah satu lantai Tahrawi di Breiji memiliki atap asbes bergelombang, jadi ketika perang dimulai, dia pindah bersama salah satu putrinya, berharap atap betonnya akan lebih terlindungi dari serangan udara Israel. Saya punya harapan besar, tapi rumah putri saya tetap terlindungi tidak dibangun pada tanggal 23 Oktober. Itu dibom.
Dua belas orang, termasuk Tahrawi, tewas seketika dan delapan lainnya luka-luka. Dia dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan internal, namun bangsal penuh dan peralatan medis terbatas, sehingga dokter memprioritaskan pemuda tersebut.
Dia meninggal seminggu kemudian, meninggalkan keluarganya. “Kakek saya tidak tergabung dalam organisasi militer mana pun dan tidak melakukan kejahatan apa pun,” kata sang cucu. “Dia hanyalah seorang lelaki tua yang tidak bisa menyakiti siapa pun.”
Ketika perang di Gaza dimulai, Taharwi memiliki 126 keturunan yang masih hidup, namun hanya 90 yang selamat tahun ini. Saat meninggal, cucu tertuanya berusia 53 tahun dan cicit tertuanya berusia 5 tahun.
Abd al-Rahman al-Tahrawi berusia 26 tahun, berasal dari tengah marga besar, dan seumuran dengan kakeknya saat mengungsi ke Gaza. Kengerian yang dia tahu dari cerita-cerita lama kini menjadi hidupnya sendiri. Keluarganya telah dievakuasi enam kali di Jalur Gaza, dan kakeknya tidak lagi berada di sana untuk memberikan dukungan dan inspirasi.
“Ketika saya kehilangan kakek saya, saya merasa sangat sedih dan sangat hampa,” katanya. “Saya adalah favoritnya. Saya akan merindukan dia dan kisah petualangannya, pertemuan kami, dan tawanya.”
Anda adalah Walid Samir Al Sabah
Waad belum lahir ketika ibunya, Salam al-Sabah, terkubur di bawah longsoran puing akibat serangan udara Israel. Serangan udara tanggal 15 Februari menargetkan rumah-rumah tetangga, namun bomnya sangat besar sehingga sebagian rumah keluarga Saba juga hancur.
Tim penyelamat bergegas ke lokasi kejadian, namun butuh lebih dari satu jam untuk membebaskan Saba, yang sedang hamil sembilan bulan, karena mereka harus bekerja tanpa alat berat. Sebagai ibu dari empat orang putra, ia berharap bisa bertemu dengan putri sulungnya dalam beberapa hari ke depan.
Pamannya yang sudah menikah, Eid Saba, adalah direktur keperawatan di Rumah Sakit Kamal Adwan. Dia sedang bekerja ketika kerabatnya dibawa masuk, tertutup debu dan jelaga akibat ledakan, jadi dia tidak mengenali mereka pada awalnya.
“Saya baru menyadari siapa mereka ketika beberapa dari mereka mulai meneriakkan nama saya. Saya sempat membeku karena terkejut, namun kemudian saya cukup pulih untuk memulai tes,” katanya.
Keponakannya sudah terlambat, namun janin dalam kandungannya masih berjuang untuk bertahan hidup, sehingga dokter melakukan operasi caesar darurat dan membawa Waad ke perawatan intensif. Dia bertahan selama dua jam.
“Yang paling membuat saya sedih adalah akta kelahiran dan kematian Waad diterbitkan pada waktu yang bersamaan,” kata Eid Sabaha. Ia menambahkan, ibu dan putrinya bisa selamat jika mereka mendapat perawatan lebih cepat.
Keduanya dimakamkan di kuburan bersama di samping putra Salam yang berusia 11 tahun, Acid, terbungkus Kain Kafan, Salam memegang Ward.
Pada awal perang, keluarga tersebut dievakuasi dari rumah mereka di kota utara Tal al-Zaatar mengikuti perintah evakuasi Israel di daerah tersebut, dan menghabiskan beberapa bulan berpindah dari rumah kerabat mereka ke tempat penampungan pengungsi.
Pengalaman serupa juga dialami Salam Al Sabah dari kakek dan neneknya semasa kecil. Pada tahun 1948, mereka meninggalkan rumah mereka di desa Brail, sekitar 19 mil sebelah utara perbatasan Israel dengan Gaza, dan menetap di kamp pengungsi Jabaliya.
Saba sedang mengandung Waad selama lima bulan ketika perang Israel-Gaza dimulai, dan perjalanan menjadi semakin sulit. Setelah tentara Israel mundur dari daerah tersebut, keluarga tersebut memutuskan untuk kembali, meskipun bangunannya rusak parah luar dan dalam.
Setidaknya itu adalah rumah mereka, pikir mereka, dan relatif aman. Kemudian, pada tanggal 15 Februari, Israel mengebom kompleks di dekatnya tanpa peringatan, kata pamannya.
“Rumah yang dibom itu kosong. Saya bisa saja memperingatkan pemilik rumah tetangga untuk mengungsi. Jika saya melakukannya, kerabat saya masih hidup dan saya akan mendengar tawa dan tangisan Waad kecil. tempat.”